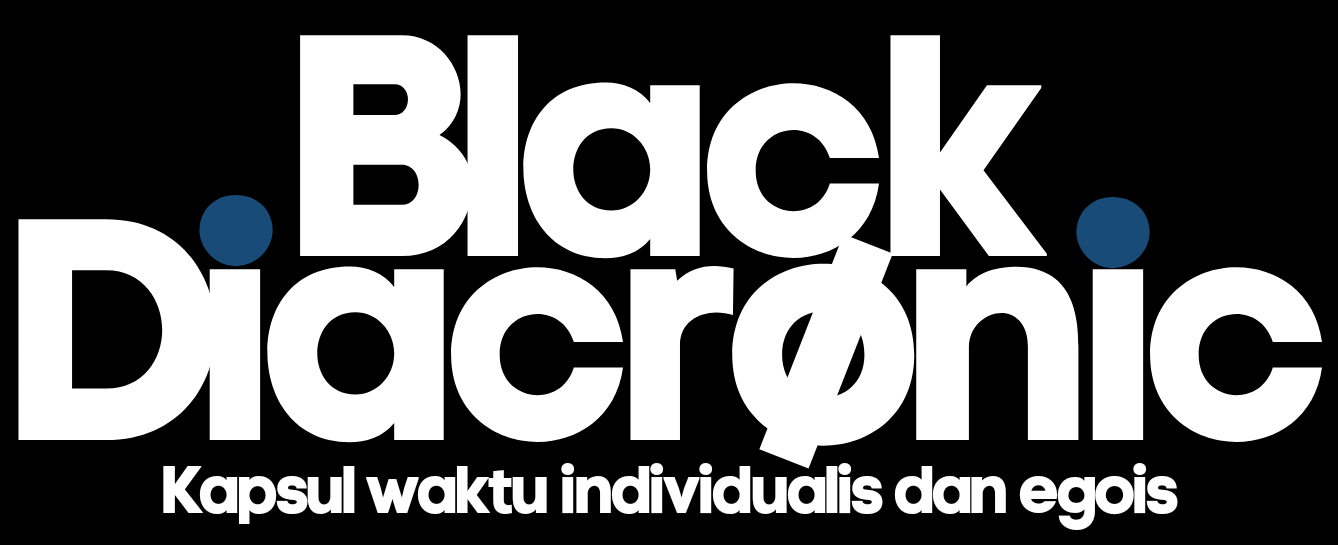Paper ini bertujuan untuk mengeksplorasi logika pluralisme-empiris dalam karya Gilles Deleuze dan Max Stirner. Keduanya adalah pemikir yang jarang dihubungkan. Pemikiran Stirner muncul, bersama dengan pemikiran Marx, berasal dari bayang-bayang Hegelianisme. Namun, ketika Marx mencoba membalikkan Hegel pada garis sosialis dan kolektivis, Stirner mengembangkan kritik terhadap Idealisme Jerman yang sangat individualistis dan menentang persatuan konseptual. Filsafat egoismenya adalah pertahanan terhadap perbedaan individu dari serangan ide-ide dan abstraksi esensialis—seperti sosialisme dan humanisme—‘hantu’ idealisme yang telah meletakkan individu ke dalam satu bentuk umum atau lainnya. Di sisi lain, Deleuze dihubungkan dengan Foucault dan Derrida sebagai salah satu pemikir poststrukturalis kontemporer yang paling berpengaruh, sedangkan Stirner umumnya tidak dianggap sebagai poststrukturalis dan kurang mendapat perhatian dari sudut pandang teori kontemporer. Deleuze biasanya dianggap sebagai filsuf perbedaan. Kritiknya terhadap abstraksi konseptual dan perayaan multipel dan korporeal melibatkan banyak bidang yang berbeda, dari politik dan psikoanalisis, hingga teori sastra dan film. Namun, justru dalam penilaian atas perbedaan, korporealitas dan penolakan terhadap abstraksi idealis inilah, bidang pertemuan yang penting dengan Stirner muncul. Pemikiran Deleuze dapat dilihat sebagai perpanjangan logis dari upaya Stirner untuk mengusir ‘hantu’ idealisme dan esensialisme dari pemikiran. Deleuze, dalam karyanya tentang Nietzsche, mengacu pada Stirner sebagai “ahli dialektika yang mengungkapkan nihilisme sebagai kebenaran dialektika” (Deleuze: 1992). Stirner mengarahkan dialektika di atas kepalanya, mengungkapkan sebagai puncak dan esensinya, bukan sebagai semangat rasionalitas, tetapi sebagai egois; korporeal; individu yang unik. Bagi Stirner, dialektika tidak menghasilkan kelahiran cita-cita yang agung (grand ideal), tetapi mengarah kepada kematiannya. Alih-alih mengatasi perbedaan dan singularitas, dialektika sebenarnya adalah kemenangan terakhir bagi cita-cita yang agung. Deleuze melanjutkan pembalikan idealisme dan abstraksi konseptual ini.
Paper ini akan mengeksplorasi dan mengembangkan bidang pertemuan ini, untuk melihat ke mana arahnya. Saya akan melakukan ini dengan cara berikut: Pertama, saya akan memperluas konsep pluralisme empiris melalui diskusi tentang kritik representasi Stirner dan Deleuze. Kedua, Saya akan melihat implikasi politik dari kritik terhadap idealisme, melalui eksplorasi kekuasaan negara dan penindasannya serta penghapusan perbedaan individu. Ketiga, saya akan mencoba mengembangkan, dari pemikiran Stirner dan Deleuze, sebuah politik dan etika multiplisitas serta korporealitas melalui gagasan singularitas.
Saul Newman
Kritik Representasi
Ketika Deleuze berkata, “Saya seorang empiris, yaitu pluralis”, apa maksudnya? Empirisme adalah pengutamaan korporeal, sensual dan material di atas yang abstrak, ideal dan supernatural. Pluralisme menekankan pluralitas, multiplisitas dan perbedaan atas persatuan, kesamaan dan sentralitas. Maka, pluralisme empiris dapat dilihat sebagai pernyataan filosofis dari ‘prinsip’ material tentang perbedaan dan pluralitas. Deleuze dan Stirner, dengan cara berbeda, adalah eksponen dari prinsip tersebut. Namun istilah ‘prinsip’ agak menyesatkan jika menyarankan konseptualisasi perbedaan yang abstrak. Stirner dan Deleuze menolak abstraksi dan konsepsi, justru karena ia menolak perbedaan dan pluralitas. Mereka berusaha untuk berteori, dengan kata lain, perbedaan non-konseptual, perbedaan yang melebihi batas konseptual. Mereka menolak untuk ‘mensterilkan luka5’ dalam berpikir dengan memaksakan konsep dan ideal, alih-alih membiarkan intensitas mendalam dunia bocor, membentuk anak sungai yang aneh dan tak terduga dalam akal sehat. Bagi mereka, kehidupan mengasumsikan intensitas yang lebih besar, realitas yang lebih nyata daripada konsep dan definisi, yang dengan putus asa, berusaha menjelaskannya. Jadi bagi Deleuze, terdapat perbedaan kualitatif antara perbedaan realitas dan perbedaan konseptual; antara perbedaan itu sendiri dan perbedaannya dalam konsep umum. Dia bertanya: “apa konsep perbedaan—yang tidak dapat direduksi menjadi perbedaan konseptual sederhana tetapi menuntut gagasannya sendiri, singularitasnya sendiri pada tingkat gagasan?” (Deleuze: 1994). Saya berpendapat bahwa perbedaan non-konseptual yang menuntut singularitasnya sendiri ini, dapat diteorikan dalam kerangka gagasan tentang ‘keunikan’ milik Stirner. Keunikan, seperti yang akan kita lihat, adalah bentuk individualitas yang tidak dapat direduksi menjadi gagasan umum. Oleh karena itu, perbedaan bagi Stirner dan Deleuze adalah non-konseptual dan material. Ia adalah perbedaan yang ‘nyata’, yang bertentangan dengan abstraksi konseptual tentang perbedaan yang menyangkal korporeal. Perbedaan krusial ini muncul melalui kritik terhadap representasi.
Dalam Difference and Repetition (1968), Deleuze melakukan kritik terhadap pemikiran representatif. Dia berpendapat bahwa representasi membatasi pemikiran dan menyangkal perbedaan. Ini dikarenakan dalam pemikiran representasi, perbedaan selalu dipahami sebagai perbedaan dari sesuatu, perbedaan dari ‘yang sama’. Jadi, perbedaan selalu merupakan repetisi yang buruk dari gagasan orisinal—perbedaan itu sendiri tidak pernah menjadi perbedaan. Deleuze memulainya dengan membedakan repetisi (repetiton) dari generalitas (generality). Generalitas menganut dua tatanan utama: urutan kemiripan, dan urutan kesetaraan (Deleuze: 1994). Generalitas berarti, satu istilah dapat diganti dengan yang lain. Di sisi lain, repetisi mengacu pada apa yang tidak dapat digantikan atau disubstitusikan. Repetisi adalah perilaku dalam hubungannya dengan bentuk tunggal—sesuatu yang tidak memiliki padanan dan tidak dapat ditukar dengan yang lain. Ia ada dengan sendirinya. Setiap istilah yang diulang berbeda jenisnya dari yang sebelumnya. Deleuze kemudian mengatakan: “Jika pertukaran adalah kriteria dari generalitas; pencurian dan pemberian adalah repetisi” (Deleuze: 1994). Sementara generalitas adalah penerapan hukum yang membosankan, misalnya kesetaraan subjek di depan hukum, maka repetisi mempertanyakan hukum pertukaran ini dengan merayakan yang tunggal, pengecualian terhadap aturan tersebut.
Menurut Deleuze, repetisi dan generalitas juga bertentangan dari perspektif representasi. Representasi adalah hubungan suatu konsep dengan objeknya. Bagaimanapun logika ini bekerja dalam pengertian ganda: selalu ada satu konsep untuk setiap objek tertentu; dan di sisi lain, hanya ada satu objek untuk satu konsep. Logika representasi ganda ini membangun gagasan perbedaan sebagai perbedaan konseptual. Bagi Deleuze, paradoksnya perbedaan konseptual ini memfasilitasi kemiripan dan generalitas daripada perbedaan itu sendiri. Generalitas adalah pernyataan kekuatan konsep tak terbatas untuk mengekspresikan dan merepresentasikan objek, sedangkan repetisi memblokir dan membatasi representasi yang tak terbatas ini. Dari repetisi yang memiliki kemampuan untuk mendefinisikan dirinya sendiri, muncullah repetisi sebagai perbedaan non-konseptual. Perbedaan non-konseptual adalah perbedaan yang keluar dari tatanan konseptual. Dalam kata-kata Deleuze: “ia mengungkapkan kekuatan yang khas pada yang ada, keras kepala dari yang ada dalam intuisi, yang menolak setiap spesifikasi dengan konsep tidak peduli seberapa jauh hal ini dapat diambil” (Deleuze: 1994). Oleh karena itu, repetisi adalah perbedaan tanpa konsep untuk menjelaskannya—suatu bentuk perbedaan itu sendiri. Ia selalu melebihi gagasan, mencari perubahannya di bagian luarnya. Namun harus diperjelas, bahwa bentuk perbedaan ini bukanlah perbedaan yang mutlak di luar gagasan, karena ia hanya menegaskan kembali gagasan dalam eksterioritas oposisi. Sebaliknya, perbedaan non-konseptual ada di dalam gagasan, namun selalu melampauinya. Ia adalah gerakan singularitas yang bermain di balik topeng generalitas, selalu tumpah dari balik tepinya.
Maka orang harus waspada terhadap penegasan mutlak perbedaan atas persamaan. Untuk menegaskan sisi hierarki yang tersubordinasi sering kali harus memulihkan hierarki itu sendiri, dalam arti yang terbalik. Melakukan pelanggaran mutlak berarti menegaskan kembali hal yang dilanggar. Dengan cara ini, perbedaan hanya akan menjadi identitas mutlak lainnya, dengan kata lain, menjadi ‘yang sama’. Deleuze kemudian berkata: “Seorang budak tidak berhenti menjadi budak dengan mengambil alih kekuasaan” (Deleuze: 1994). Bagi Nietzsche, menjadi budak adalah kualitas ketidakberdayaan, terlepas dari tempat ia dalam tingkatan hierarki. Dengan cara yang sama, jika perbedaan hanya ditegaskan di atas kesamaan tanpa mempengaruhi reevaluasi itu sendiri, ia hanya menjadi identitas lain dari ‘yang sama’. Ia tetap menjadi ‘budak’ dari hierarki yang telah diciptakannya kembali. Oleh karena itu, perbedaan harus berbeda secara kualitatif. Ia harus dipikirkan ulang dengan cara menahan penyerapan kembali ke dalam struktur identitas. Perbedaan harus mengubah persyaratan hierarki. Jadi, karena Deleuze telah menghargai perbedaan di atas generalitas, ia telah melampaui opsisi biner; perbedaan dan persamaan. Todd May memperkuat poin ini. Dia berpendapat bahwa Deleuze tidak mengemukakan dunia perbedaan mutlak karena ia akan membuat perbedaan konsep metafisik dan abstrak yang berdiri di atas segalanya—sesuatu yang akan ditolak oleh Deleuze (May: 1997). Jadi, daripada perbedaan menjadi konsep mutlak dan menjadi identitas esensial, ia harus tetap terbuka untuk ‘yang lain’—terbuka bahkan untuk kemungkinan ‘yang sama’. Dengan cara ini, perbedaan menjadi perbedaan itu sendiri, bukan perbedaan yang bertentangan dengan ‘yang sama’. Ia akan menjadi perbedaan Nietzschean yang, tidak seperti representasi, tidak membutuhkan identitas eksternal untuk menentangnya guna menegaskan dirinya sendiri. Dengan cara ini, Deleuze memperkenalkan prinsip perbedaan yang tidak hanya menolak generalisasi konseptual, tetapi juga menolak kecenderungannya sendiri terhadap kemutlakan konseptual.
Maka melalui pembedaan antara repetisi dan generalitas, telah muncul prinsip perbedaan non-konseptual, perbedaan yang tidak dapat ditorehkan dalam struktur generalitas. Ia mungkin dianggap sebagai ekses yang menentang batasan konsep. Ia menunjukkan serangan terhadap logika representasi itu sendiri. Konsep tidak dapat lagi mewakili perbedaanyang sebenarnya secara memadai. Bagi Deleuze, perbedaan adalah yang utama, sedangkan representasi adalah yang kedua: “perbedaan ada di balik segalanya, tetapi di balik perbedaan tidak ada apa-apa” (Deleuze: 1994). Deleuze terlibat dalam kritik terhadap Hegelianisme, yang mengutamakan gagasan/ide daripada perbedaan empiris (Baugh: 1992). Perbedaan Hegel terlihat dari segi kontradiksi yang selalu diselesaikan secara dialektis. Perbedaan dengan demikian dihilangkan dengan dialektika kembali menjadi identitas universal-esensial yang logikanya terbuka. Deleuze berpendapat bahwa melihat perbedaan dalam istilah kontradiksi berarti menyangkal perbedaan. Perbedaan tidak dapat dimasukkan dalam struktur representasi dari dialektika—perbedaan selalu merupakan perbedaan dalam dirinya sendiri. Dengan cara yang sama, Deleuze juga menolak filsafat Platonis tentang bentuk-bentuk abstrak. Bagi Platon, hanya bentuk abstrak yang benar-benar nyata sementara objek material hanyalah salinan dari bentuk dan dengan demikian ia terdegradasi. Perbedaan lebih jauh lagi direndahkan, menurut model representasi ini, dengan menjadi salinan yang tidak sempurna. Namun Deleuze berpendapat bahwa dunia bentuk yang teratur dirusak oleh ‘yang lain’: simulakra.
Jadi representasi didasarkan pada sentralitas dan dominasi identitas. Namun, seperti yang ditunjukkan Deleuze, dominasi ini sedang runtuh. Identitas esensial yang menjelaskan dunia akan dipertanyakan. Kita hidup di dunia simulakra, di mana identitas hanya disimulasikan—mereka adalah topeng untuk permainan perbedaan dan singularitas yang menyusunnya. Repetisi tidak termasuk dalam urutan representasi karena alasan ini. Karena tidak ada model atau identitas asli untuk diulang, ada permainan tanda dan simbol yang tak ada habisnya—singkirkan satu topeng dan yang ditemukan di bawahnya, bukan esensinya, tetapi topeng yang lain. Tidak ada kemungkinan untuk mendapatkan yang orisinal, esensi primer atau keberadaan di balik repetisi, karena esensi ini tidak ada. Ia sendiri adalah repetisi atau representasi lain; logika representasi ditumbangkan dengan memperluasnya hingga tak terbatas. Oleh karena itu, konsep dan generalitaslah yang dianggap merepresentasikan dunia, diremehkan. Dunia seluruhnya terdiri dari perbedaan; perbedaan yang tidak membutuhkan konsep yang mengatur untuk merepresentasikannya. Perbedaan ini tidak setara, bukan dalam arti dibandingkan dengan standar atau norma universal, tetapi dalam arti berbeda satu sama lain dalam distribusi dan efek. Inilah yang Deleuze sebut sebagai ‘distribusi nomadik’ (nomadic distribution)—distribusi di ruang terbuka, tanpa konsep tatanan pusat (Deleuze: 1994). Segala sesuatu di dunia ini sudah berbeda dari yang lainnya—di sini tidak perlu ada konsep perbedaan untuk menjelaskan hal ini. Perbedaan dapat dialami dan dirasakan secara langsung. Ia mengacu pada dunia korporeal dan masuk akal—realitas empiris yang tidak dapat dimasukkan dalam bentuk abstrak dan struktur representasi. Bagi Deleuze:
Representasi gagal menangkap dunia perbedaan yang ditegaskan. Representasi hanya memiliki satu pusat, perspektif yang unik dan surut, dan akibatnya memiliki kedalaman yang salah. Ia menengahi segalanya, tetapi tidak memobilisasi dan menggerakkan apa pun. Gerakan, pada bagiannya, menyiratkan pluralitas pusat, superposisi perspektif, jalinan sudut pandang, koeksistensi momen yang pada dasarnya mendistorsi representasi (Deleuze: 1994).
Sejumlah poin penting muncul dari kritik Deleuze terhadap representasi. Pertama, gagasan tentang perbedaan non-konseptual, atau perbedaan itu sendiri terbukti. Ini adalah perbedaan yang, seperti telah kita lihat, melebihi struktur konseptual, karena tidak membutuhkan generalisasi. Ia menantang aturan konsep atas apa yang dimaksudkan untuk direpresentasikan. Kedua, adanya transformasi prinsip perbedaan itu sendiri. Perbedaan tidak lagi menjadi identitas pertentangan terhadap identitas dominan yang sama. Ia, seperti yang telah kita lihat, hanya menegaskan kembali struktur hierarki identitas. Sebaliknya, perbedaan diubah dengan cara mendekonstruksi oposisi biner. Ketiga, prinsip perbedaan non-konseptual ini menjadi dasar bagi pluralisme empiris. Identitas konseptual, seperti yang telah kita lihat, terdiri dari pluralitas yang sebenarnya, perbedaan dan singularitas konkret. Konsep dan abstraksi hanyalah topeng yang menyembunyikan yang masuk akal, materialitas plural—dunia perbedaan dan intensitas yang sebenarnya. Terdapat korporeal imanen yang menentang semua upaya representasi. Otoritas konsep abstrak atas aktualitas empiris dengan demikian ditumbangkan; empirisme ini juga transendental. Patrick Hayden mendefinisikan empirisme transendental sebagai “ontologi yang didasarkan pada keunggulan perbedaan” (Hayden: 1998). Jadi, pluralisme-empiris Deleuze adalah transendental karena mengandaikan ontologi perbedaan. Dengan kata lain, perbedaan adalah prinsip utama yang mendasari pluralitas dunia empiris.
Deleuze tertarik pada kondisi yang sebenarnya dari pengalaman aktual. Dia melihat abstraksi, konsep dan generalitas sebagai upaya untuk menyangkal kondisi pengalaman ini dengan melihatnya sebagai refleksi dari esensi atau gagasan sentral. Jadi, bagi Idealis, partikularitas empiris hanyalah aktualisasi dari gagasan. Namun bagi Deleuze, aktualitas adalah singularitas nyata, dengan syarat dan ketentuan keberadaannya sendiri. Prinsip multiplisitas digunakan di sini untuk menggambarkan kondisi keberadaan material. Multiplisitas diatur oleh logika perbedaan sebagai hubungan kontingen antara aktualitas. Realitas empiris dibentuk oleh multiplisitas dengan cara ini—ia dibentuk melalui pengaturan kekuatan dan intensitas yang kontingen.
Representasi adalah cara berpikir yang menyangkal multiplisitas dan pluralitas yang imanen. Ia didasarkan pada model atau citra aborescent7 yang menentukan pemikiran sebelumnya secara rasional (Deleuze, Parnet: 1987). Strukturnya seperti sistem akar dan pohon: ada kesatuan pusat, kebenaran atau esensi—seperti rasionalitas—yang merupakan akar, dan yang menentukan pertumbuhan cabang-cabangnya. Model ini mengandaikan identitas sentral. Ini menjebak pemikiran dalam identitas biner yang berlawanan seperti hitam dan putih; laki-laki dan perempuan; heteroseksual dan homoseksual. Pikiran harus selalu terbuka menurut logika dialektis dan dengan demikian terjebak dalam divisi biner yang menolak perbedaan dan pluralitas. Model aborescent kemudian menjadi dasar bagi abstraksi dan konsep umum yang mendominasi pemikiran kita.
Hantu Idealisme
Stirner terlibat dalam kritik serupa terhadap representasi. Dia mengklaim bahwa abstraksi dan konsep umum adalah fiksi yang menyangkal sensualitas korporeal dan perbedaan kehidupan. Stirner menegaskan perbedaan dan singularitas, melihatnya sebagai elemen utama dari realitas empiris. Dalam pengertian ini, dia mungkin terlihat menganut pluralisme-empiris yang mirip dengan Deleuze. Abstraksi seperti kebenaran, rasionalitas, moralitas dan esensi manusia adalah hantu (spook) yang tidak memiliki realitas material, tetapi mencoba membuat perbedaan individu sesuai dengan prinsip mereka. Bagi Stirner, dunia ini penuh dengan hantu-hantu tersebut; abstraksi ideal yang merusak pengalaman sensual. Kita dihantui oleh hantu-hantu yang bukan buatan kita sendiri, tetapi yang mendominasi pikiran kita:
Lihatlah secara dekat atau jauh, dunia hantu mengelilingi Anda di mana-mana; Anda selalu mengalami “penampakan” atau penglihatan. Segala sesuatu yang tampak nyata bagi Anda hanyalah khayalan dari roh yang berdiam, adalah “penampakan” hantu; dunia bagi Anda hanyalah sebuah “dunia penampilan”, di belakangnya roh berjalan (Stirner: 1995)
Dengan kata lain, keyakinan bahwa ada esensi di balik segalanya, kebenaran yang lebih dalam yang akan ditemukan di balik permukaan, merupakan indikasi sejauh mana hantu idealisme telah merasuki pikiran kita. Stirner berpendapat bahwa mempercayai ‘esensi’ berarti menyangkal pengalaman sensual yang nyata. Tidak ada sesuatu pun di luar permukaan selain permukaan lain dan mencari sesuatu di luar permukaan berarti menyangkal kehidupan itu sendiri. Kritik Stirner terhadap representasi terbukti di sini. Jika kita melihat dunia korporeal kita hanya sebagai refleksi atau representasi dari konsep esensial, kita menyangkal realitas ini dan mencari ‘penampakan’. Bertentangan dengan filsafat idealisme, yang menganggap dunia luar hanya sebagai ‘penampakan’ atau cerminan dari kebenaran atau gagasan esensial, Stirner ingin menyatakan bahwa kebenaran esensial inilah yang menjadi penampakan itu sendiri. Selain itu, ia adalah penampakan yang menindas dan merusak karena mengasingkan individu dari realitas sensualnya dengan membuatnya mencari esensi yang sebenarnya tidak ada.
Kritik Stirner terhadap idealisme dan pemikiran representatif berkembang dari kritiknya terhadap humanisme Feuerbachian. Dalam Essence of Christianity (1841), Feuerbach menerapkan pengertian alienasi pada agama. Menurut Feuerbach, agama itu mengasingkan karena ia mengharuskan manusia melepaskan kualitas dan kekuatannya sendiri dengan memproyeksikannya kepada Tuhan yang abstrak di luar jangkauan manusia. Dengan melakukan itu, manusia menggantikan dirinya yang esensial, membuatnya terasing dan direndahkan. Kualitas manusia menjadi kualitas Tuhan. Feuerbach berpendapat bahwa predikat Tuhan sebenarnya hanya predikat manusia sebagai makhluk spesies, dan Tuhanlah yang melakukan hipostatisasi8 manusia. Sementara manusia harus menjadi satu-satunya kriteria untuk kebenaran, cinta dan kebajikan, karakteristik ini sekarang menjadi milik makhluk abstrak yang menjadi satu-satunya kriteria bagi mereka. Namun Stirner berpendapat bahwa dalam mengklaim kualitas yang kita kaitkan dengan Tuhan atau Yang Mutlak sebenarnya adalah kualitas manusia, Feuerbach telah membuat manusia menjadi makhluk yang maha kuasa. Feuerbach mewujudkan proyek humanisme Abad Pencerahan untuk kembali menempatkan manusia ke tempat yang selayaknya di pusat alam semesta. Namun, justru upaya menjadikan manusia sebagai Tuhan, untuk menjadikannya sebagai yang terbatas menjadi yang tak terbatas, adalah yang dikutuk Stirner. Menurut Stirner, alih-alih Feuerbach mengklaim telah menggulingkan agama, ia hanya membalikkan urutan subjek dan predikat, ia tidak melakukan apa pun untuk menghancurkan otoritas agama itu sendiri. Kategori yang mengasingkan Tuhan dipertahankan dan dikuatkan dengan menanamkannya di dalam diri manusia. Dengan demikian, manusia merebut posisi Tuhan, menangkapnya untuk dirinya sendiri sebagai kategori yang tak terbatas; manusia menjadi pengganti ilusi Kristen. Stirner berkata:
Makhluk tertinggi memang esensi manusia, tetapi hanya karena dia adalah esensinya dan bukan dia sendiri. Tetap tidak penting apakah kita melihatnya di luar dirinya dan melihatnya sebagai ‘Tuhan’, atau menemukannya di dalam dirinya dan menyebutnya ‘ esensi manusia’ atau manusia. Saya bukan Tuhan atau Manusia, bukan esensi tertinggi maupun esensi yang saya miliki. Oleh karena itu, semuanya adalah satu yang utama apakah saya memikirkan esensi seperti di dalam diri saya atau di luar saya (Stirner: 1995).
Jadi bagi Stirner, esensi adalah sesuatu yang berada di luar individu konkret dan dengan mencari yang sakral dalam ‘esensi manusia’, dengan menempatkan manusia esensial dan mengatribusikan kepadanya kualitas-kualitas tertentu yang sampai sekarang telah dikaitkan dengan Tuhan, Feuerbach hanya memperkenalkan kembali keterasingan agama. Individu konkret menemukan dirinya terasing sekali lagi ke abstraksi di luar dirinya—kali ini esensi manusia bukan esensi ilahi. Stirner menunjukkan bahwa dengan membuat karakteristik dan kualitas tertentu penting bagi Manusia, Feuerbach telah mengasingkan mereka yang tidak memiliki kualitas tersebut. Maka manusia menjadi seperti Tuhan dan manusia direndahkan di bawah Tuhan. Demikian pula individu yang konkret direndahkan di bawah makhluk yang sempurna ini, manusia. Bagi Stirner, manusia sama menindasnya, jika tidak lebih, daripada Tuhan. Manusia adalah abstraksi idealis baru yang menyangkal materialitas yang masuk akal dari individu yang mengklaim ‘berbicara untuk dirinya sendiri’, untuk merepresentasikan dirinya. Ia adalah hantu atau gagasan tetap (fixed idea)—sesuatu yang menodai keunikan individu dengan membandingkannya dengan ideal yang bukan ciptaannya sendiri.
Kritik representasi ini meluas ke semua abstraksi, termasuk kebenaran rasional dan moralitas. Kebenaran rasional selalu dipegang di atas perspektif individu dan Stirner berpendapat bahwa ini adalah penyangkalan lebih lanjut atas perbedaan individu. Stirner tidak serta merta menentang kebenaran itu sendiri, melainkan karena kebenaran itu telah menjadi suatu ideal yang abstrak dan sakral, disingkirkan dari cengkeraman individu dan digunakan secara tiranik di atas pluralitas perspektif. Stirner berkata: “Selama Anda percaya pada kebenaran, Anda tidak percaya pada diri sendiri dan Anda adalah seorang hamba, seorang yang religius” (Stirner: 1995). Maksudnya adalah, percaya mutlak pada kebenaran rasional berarti menundukkan diri pada abstraksi yang menyangkal dunia korporeal. Seperti Deleuze, Stirner percaya bahwa generalisasi seperti kebenaran rasional, yang tampaknya bersatu, sebenarnya terdiri dari pluralitas perbedaan. Stirner menolak gagasan tetap seperti kebenaran rasional dan moralitas, dari perspektif perbedaan individu atau ‘keunikan’. Seperti Deleuze, Stirner melihat perbedaan individu sebagai yang utama—dasar bagi pluralitas dan multiplisitas dunia empiris. Abstraksi dan gagasan tetap dikutuk karena mereka memasukkan perbedaan individu dalam generalitas mereka, sehingga menyangkal ‘keunikan’. Dengan cara ini, generalitas manusia menyangkal individu konkret:
Manusia menjangkau melampaui setiap individu manusia, namun—meskipun dia menjadi ‘esensinya’—pada kenyataannya, ia bukanlah esensinya (yang lebih sika sendiri, sepertihalnya dia sebagai individu), tetapi seorang ‘jenderal’ dan yang lebih tinggi darinya. Bagi orang ateis, ia adalah ‘esensi tertinggi’ (Stirner: 1995)
Dengan kata lain, bagi Stirner esensi sebenarnya dari individu adalah sesuatu yang tunggal dan unik seperti halnya individu itu sendiri. Ini adalah ‘esensi’ yang secara paradoks menyangkal esensi karena tidak mengacu pada generalitas abstrak di luar dirinya sendiri. Keunikan dapat dilihat sebagai bentuk perbedaan non-konseptual, dengan cara yang mirip dengan Deleuze. Ia adalah perbedaan yang didefinisikan melalui pengalaman perbedaan yang nyata dan empiris, dan bukan melalui konsep perbedaan yang abstrak. Bagi Stirner, Unit dasar diferensiasi adalah ‘Yang Unik’ atau ego. Ego lebih dari individu konkret—ia adalah prinsip perbedaan itu sendiri. Seperti prinsip Deleuze tentang perbedaan non-konseptual, ego melampaui batas konsep; tidak memerlukan generalisasi eksternal: “tidak ada konsep yang mampu menjelaska diri saya” (Stirner: 1995). Stirner ingin melampaui esensi yang hanyalah topeng lain, repetisi lain, sampai seseorang menemukan keindividuannya, fondasi bagi Yang Unik. Namun, individu bukanlah esensi melainkan prinsip perbedaan murni yang menyangkal esensi. Mencari esensi berarti menyangkal realitas empiris konkret dunia. Stirner mengatakan:
Ketika seseorang melihat ke dasar segala sesuatu, mencari esensinya, dia sering kali menemukan sesuatu yang berbeda dari yang terlihat; ucapan manis dan hati yang berbohong, kata-kata sombong dan pikiran yang hina dan sebagainya. Dengan menonjolkan esensi, seseorang merendahkan penampilan yang sampai sekarang salah dipahami menjadi sekadar kemiripan, sebuah tipu daya. Inti dari dunia, bagi dia yang melihat. (Stirner: 1995)
Dengan kata lain, tidak ada esensi pada inti keberadaan—yang ada hanyalah kekosongan. Menurut Stirner, esensi dunia yang sebenarnya justru adalah pengalaman konkret—“perbuatan dunia”—yang direduksi menjadi penipuan melalui pencarian esensi. Kekosongan di dasar keberadaan ini adalah ketiadaan kreatif (Creative Nothingness), sebuah prinsip perbedaan yang melaluinya pluralitas dan multiplisitas baru dapat dibentuk.
Dapat dikatakan, bahwa ego Stirner sebagai prinsip perbedaan adalah mitra logis dari prinsip Deleuze tentang perbedaan non-konseptual. Keduanya menandakan perbedaan dalam dirinya sendiri—perbedaan yang menentang logika representasi. Apalagi keduanya merupakan aktualisasi perbedaan yang mengarah pada konstruksi multiplisitas dan pluralitas baru. Mereka adalah prinsip-prinsip yang menentukan dunia pengalaman empiris yang nyata. Oleh karena itu, Stirner dan Deleuze melalui kritik representasi, mengembangkan logika pluralisme empiris yang merongrong abstraksi dan gagasan tetap yang mendominasi kita. Diskusi sekarang akan beralih ke implikasi politik dari kritik representasi ini.
Kritik terhadap Negara
Saya berpendapat bahwa Stirner dan Deleuze terlibat dalam kritik representasi yang berusaha membebaskan pemikiran dari citra idealis yang menyangkal perbedaan empiris. Bagi Deleuze, citra pemikiran yang aborescent adalah bidang konseptual otoriter yang di atasnya wacana sentralis dan esensialis seperti pengetahuan rasional didasarkan. Wacana ini terkait erat dengan kekuasaan politik. Dan bagi Stirner juga, wacana esensialis seperti kebenaran dan moralitas, pasti terkait dengan kekuatan politik dan praktik penindasan diri.
Ekspresi politik dari otoritarianisme konseptual ini adalah negara. Bagi Stirner dan Deleuze, negara adalah seperangkat alat yang sangat menindas dan musuh bagi kehidupan korporeal dan plural. Negara adalah perwujudan dari kesatuan konseptual yang menyangkal kehidupan dengan memasukkannya ke dalam struktur sentralis dan esensialisnya, dan yang memberikan landasan bagi serangkaian wacana dan praktik dominasi. Sebagai abstraksi, negara melampaui manifestasi konkretnya yang berbeda, namun pada saat yang sama beroperasi melaluinya. Negara lebih dari sekedar institusi yang ada dalam panggung sejarah. Ia adalah prinsip abstrak kekuasaan dan otoritas yang selalu ada dalam berbagai bentuk, namun entah bagaimana melebihi dari aktualisasinya. Misalnya, penolakan Stirner terhadap negara melampaui kritik terhadap negara tertentu—seperti negara liberal atau negara sosialis. Alih-alih, ia merupakan serangan terhadap negara itu sendiri—kategori kekuasaan negara itu sendiri, bukan hanya berbagai bentuk yang diambilnya. Menurut Stirner, apa yang harus diatasi adalah gagasan tentang kekuasaan negara itu sendiri—prinsip yang berkuasa (Stirner: 1995)
Deleuze juga menekankan otonomi konseptual negara. Dia juga melihat negara sebagai bentuk abstrak dari kekuasaan yang tidak sepenuhnya dapat diidentifikasi, khususnya dengan realisasi konkret. Deleuze mengacu pada bentuk-negara—model abstrak kekuasaan yang “mengatur ucapan dominan dan tatanan masyarakat yang mapan, bahasa dan pengetahuan yang dominan, tindakan dan perasaan konformis, segmen yang menang atas orang lain” (Deleuze, Parnet: 1987). Bagi Deleuze, negara adalah mesin abstrak dan bukan institusi konkret yang pada dasarnya ‘mengatur’ melalui institusi yang lebih kecil dan melalui praktik dominasi. Negara melakukan overcode10 dan mengatur dominasi kecil ini, mencapnya dengan jejaknya. Yang penting dari ‘mesin abstrak’ ini bukanlah bentuk kemunculannya, melainkan fungsinya yang merupakan konstitusi bidang interioritas di mana kedaulatan politik dapat dijalankan. Jadi, negara dapat dilihat sebagai proses penangkapan (Deleuze, Guattari: 1988). Bagi Deleuze, Negara adalah imanen dalam pemikiran, memberinya dasar, logos—menyediakan model yang mendefinisikan “tujuan, jalur, saluran, kanal, organ…” (Deleuze, Guattari: 1988). Selain itu, negara adalah representasi gambar pikiran, ia juga berfungsi sebagai gambar representasi subjek. Ia beroperasi melalui proses subjekifikasi, di mana individu dijadikan bagian dari citra negara dan dengan demikian dibuat terlibat dalam dominasinya sendiri. Negara melakukan ini dengan membangun citra esensial dari subjek manusia yang harus dipatuhi. Bagi Stirner, esensi manusia wacana humanis juga berfungsi sebagai normalisasi citra yang mendominasi individu dan meminggirkan perbedaan dan keunikan (Stirner: 1995). Konsep Manusia dibangun sebagai situs kekuasaan, unit politik di mana negara mendominasi individu. Negara menuntut agar individu menyesuaikan diri dengan identitas esensial tertentu sehingga ia dapat dijadikan bagian dari warga negara, dan dengan demikian, ia dapat didominasi: “Jadi negara mengkhianati permusuhannya dengan saya dengan menuntut agar saya menjadi manusia…ia memaksakan keberadaan seorang manusia atas saya sebagai sebuah kewajiban” (Stirner: 1995). Stirner telah memutuskan hubungan dengan ontologi humanisme tradisional dalam melihat ego individu dan esensi manusia sebagai entitas yang terpisah dan berlawanan. Kemanusiaan bukanlah esensi transendental. Sebaliknya, ia adalah fabrikasi kekuasaan atau setidaknya, konstruksi diskursif yang dapat dibuat untuk melayani kepentingan kekuasaan.
Deleuze, sepertihalnya Stirner, melihat subjek manusia sebagai norma representasi dan pengaruh kekuasaan, bukan identitas esensial dan otonom. Subjektivitas dikonstruksi sedemikian rupa sehingga hasratnyanya menjadi hasrat akan negara. Menurut Deleuze, negara yang dulu beroperasi melalui aparatus represif masif, sekarang tidak lagi melakukan hal tersebut—ia berfungsi melalui dominasi diri subjek. Subjek menjadi pembuat undang-undang sendiri: “semakin Anda mematuhi pernyataan realitas dominan, semakin Anda memerintahkan sebagai subjek yang berbicara dalam realitas mental, karena akhirnya Anda hanya mematuhi diri Andasendiri…bentuk perbudakan baru telah ditemukan, yaitu menjadi budak diri sendiri” (Stirner: 1995). Lebih jauh lagi, bagi Deleuze, hasrat disalurkan kepada negara melalui penyerahan kita pada ‘representasi Oedipal’. Oedipus adalah pertahanan negara terhadap hasrat yang tak terkekang (Deleuze, Guattari: 1988). Representasi Oedipal tidak menekan hasrat seperti itu, melainkan ‘merepresentasikannya’ sedemikian rupa sehingga ia percaya dirinya sendiri ditekan. Represi Oedipal hanyalah gambaran representatif yang menutupi dominasi keinginan yang sebenarnya. Bagi Deleuze, hasrat bukanlah keinginan humanis yang esensial—ia hanyalah topeng konseptual. Sebaliknya, ia menganut ontologi yang sama sekali berbeda—yang empiris transendental. Karena itu, hasrat yang ditekan dengan cara ini adalah nyata, material dan konstruktivis—ia membentuk kumpulan dengan hasrat yang lain, menciptakan keragaman yang membentuk dunia korporeal. Penindasan terhadap hasrat adalah manifestasi paling brutal dan lalim dari dominasi kehidupan empiris yang plural oleh konsep dan generalitas abstrak. Hasrat ditekan karena jika ia tidak terkekang maka ia merupakan ancaman bagi negara (Deleuze, Guattari: 1977). Representasi Oedipal mengindividualisasikan hasrat dengan memotongnya dari kemungkinan koneksi dan memenjarakannya dalam subjek individu. Bagi Stirner, ia sama seperti subjek esensial manusia yang memenjarakan ego, mencoba menangkap pluralitas dan perubahannya dalam satu konsep.
Pertanyaan tentang hasrat kemudian memainkan peran penting baik dalam pemikiran politik Deleuze maupun Stirner. Bagi keduanya, kita bisa menginginkan dominasi kita sendiri, sama seperti kita menginginkan kebebasan (Deleuze, Parnet: 1987). Hasrat tidak ditekan atau disangkal—melainkan disalurkan ke negara. Jadi bagi Stirner, hasrat dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi hasrat untuk negara (Stirner: 1995). Dengan cara ini, dominasi negara dimungkinkan melalui keterlibatan kita—melalui hasrat kita akan otoritas. Seperti Deleuze, Stirner tidak begitu tertarik pada kekuasaan itu sendiri, tetapi pada alasan mengapa kita membiarkan diri kita didominasi oleh kekuasaan. Dia ingin mempelajari cara kita berpartisipasi dalam penindasan kita sendiri dan untuk menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi atau politik—tetapi juga berakar pada kebutuhan psikologis. Ia telah tertanam jauh di dalam hati nurani kita dalam bentuk gagasan abstrak seperti negara, esensi manusia, dan moralitas. Menurut Stirner, dominasi negara bergantung pada kesediaan kita untuk membiarkannya mendominasi kita (Stirner: 1995). Negara adalah abstraksi konseptual, dan oleh karena itu ia hanyalah fiksi; ia hanya ada karena kita membiarkannya ada dan karena kita melepaskan otoritas kita sendiri, dengan cara yang sama seperti saat kita menciptakan Tuhan dengan melepaskan otoritas kita dan menempatkannya di luar diri kita. Kekuasaan negara benar-benar didasarkan pada kekuatan kita. Kekuasaan politik tidak bisa hanya bergantung pada paksaan. Ia membutuhkan hasrat kita untuk taat padanya. Hanya karena individu tidak mengakui kekuasaan, karena ia merendahkan dirinya di hadapan otoritas, maka negara akan terus ada.
Jadi bagi Stirner dan Deleuze, negara harus diatasi sebagai gagasan sebelum bisa diatasi dalam kenyataan. Negara adalah abstraksi konseptual yang tidak hanya mengatur gagasan, wacana dan pemikiran, tetapi juga ‘merepresentasikan’ individu bagi dirinya sendiri dengan cara yang sama ketika ia menyalurkan hasratnya kepada negara. Dengan cara ini, individu korporeal melakukan represi terhadap dirinya sendiri dan melanggengkan struktur konseptual yang menyangkal kehidupan.
Politik Singularitas
Pertanyaan politik yang harus dijawab dalam bacaan pluralisme-empiris Stirner dan Deleuze adalah bagaimana kita melawan dominasi? Strategi, praktik dan konsep politik apa yang tersedia bagi kita dalam perjuangan untuk hidup ini? Bagi Stirner dan Deleuze, perlawanan terhadap negara harus terjadi pada tingkat pemikiran, gagasan dan yang paling mendasar dari hasrat kita. Kita harus belajar berpikir di luar paradigma negara. Politik revolusioner di masa lalu telah gagal karena tetap terjebak dalam konseptual umum ini. Politik terperangkap dalam konsep esensialis dan struktur Manichean yang hanya pada akhirnya menegaskan kembali otoritas. Mungkin gagasan revolusi harus ditinggalkan sama sekali. Mungkin politik seharusnya tentang melarikan diri dari identitas dan generalitas esensialis daripada menegaskannya kembali. Stirner berpendapat, perlawanan terhadap negara itu harus berbentuk bukan seperti revolusi, tetapi dalam bentuk pemberontakan. Pemberontakan dimulai dengan individu yang menolak identitas esensialnya, ‘Saya’ yang melaluinya kekuasaan beroperasi: itu dimulai “dari ketidakpuasan manusia terhadap diri mereka sendiri” (Stirner: 1995). Selain itu, pemberontakan tidak bertujuan untuk menumbangkan institusi politik itu sendiri. Ia ditujukan pada individu yang menggulingkan identitas esensialnya sendiri—yang hasilnya adalah perubahan dalam tatanan politik. Gagasan pemberontakan ini melibatkan proses kemenjadian (becoming)—ini tentang terus-menerus menemukan kembali diri sendiri, daripada membatasi diri pada identitas represif esensialis.
Pemberontakan sebagai strategi melawan identitas esensialis dan generalitas abstrak memiliki banyak kesamaan dengan pemikiran politik Deleuze. Deleuze, seperti Stirner, melihat kemenjadian—menjadi selain manusia—sebagai bentuk perlawanan. Menjadi adalah proses evolusi dari dua atau lebih entitas yang terpisah—kumpulan proses dan koneksi. Gagasan ‘menjadi’ ini mirip dengan gagasan Stirner tentang ego sebagai ‘aliran’ (flux), proses perubahan berkelanjutan yang menyangkal esensi. Menjadi adalah pergeseran identitas dan himpunan secara konstan dengan identitas lain, ke titik di mana konsep identitas tidak lagi memadai untuk menggambarkannya. Kemenjadian menghasilkan ‘garis penerbangan’ yang lolos dari pengkodean status dan mengacu di luar perbedaan belaka. Oleh karena itu, jika kita ingin menolak subjekifikasi, kita harus menolak siapa kita dan menjadi orang lain (Deleuze, Parnet: 1987). Aspek penting dari ‘kerja’ perlawanan ini adalah terlibat dalam bentuk pemikiran non-otoriter—pemikiran yang menghindari abstraksi dan kesatuan konseptual. Kita harus ingat bahwa bagi Stirner dan Deleuze, pemikiran konseptual yang abstrak memfasilitasi dominasi politik. Oleh karena itu, Deleuze ingin terlibat dalam pemikiran di luar generalisasi. Untuk tujuan ini, dia menggunakan model rizomatik12 untuk melawan citra aborescent dominan dari pemikiran yang dirujuk di atas. Pikiran rizomatik menghindari abstraksi, persatuan dan konsep generalitas; mencari multiplisitas, pluralitas dan wujud. Rizomatik didasarkan pada metafora rumput, yang tumbuh sembarangan dan tidak terlihat, berlawanan dengan pertumbuhan teratur dari sistem pohon yang aborescent. Tujuan dari rizomatik adalah untuk memungkinkan pikiran “melepaskan modelnya, membuat rumputnya tumbuh—bahkan secara lokal di pinggiran” (Deleuze, Guattari: 1988). Rizomatik, dalam pengertian ini, menentang gagasan model: ia adalah multiplisitas koneksi yang tak berujung dan serampangan yang tidak didominasi oleh satu pusat atau tempat, tetapi lebih terdesentralisasi dan plural. Ia mencakup empat karakteristik: koneksi, heterogenitas, multiplisitas dan perpecahan. Ia menolak pembagian dan hierarki biner dan ia tidak diatur oleh logika dialektis yang terbuka. Dengan demikian, ia menginterogasi abstraksi yang mengatur pikiran. Oleh karena itu, Deleuze menghadirkan model pemikiran baru yang lebih sesuai dengan kondisi dunia empiris yang sebenarnya. Ia adalah model yang memperhitungkan pluralitas dan singularitas dan tidak mencoba menghapusnya dalam logika dialektis dan struktur oposisi biner. Pemikiran rizomatik menekankan pada yang pluralistik dan bergantung pada yang universal, abstrak dan esensial. Ia adalah model yang menentang abstraksi konseptual dan pemikiran representasional, sebaliknya, ia memungkinkan bermain bebas dari perbedaan dan singularitas yang beresonansi dalam realitas empiris. Pikiran rizomatik adalah pemikiran yang menentang kekuasaan, menolak untuk dibatasi olehnya. Rizomatik “tidak akan menyerahkannya kepada siapa pun, kepada kekuasaan apa pun, untuk ‘mengajukan’ pertanyaan atau ‘mengatur’ masalah” (Deleuze, Guattari: 1988).
Saya berpendapat bahwa serangan Stirner terhadap abstraksi, esensi dan gagasan tetap adalah contoh pemikiran rizomatik. Seperti Deleuze, Stirner mencari keberagaman dan perbedaan individu, daripada mencari abstraksi dan kesatuan. Abstraksi seperti kebenaran, rasionalitas dan esensi manusia, adalah gambaran yang menyangkal pluralitas dan membentuk ‘perbedaan’ menjadi ‘kesamaan’. Stirner menemukan bentuk pemikiran baru yang menekankan multiplisitas, pluralitas dan individualitas di atas universalisme dan transendentalisme. Pemikiran anti-sentralis ini mengantisipasi pendekatan Deleuze.
Gaya berpikir rizomatik ini memiliki implikasi radikal bagi teori politik. Arena politik tidak dapat lagi disusun menurut garis pertempuran tradisional kekuasaan politik terpusat dan subjek otonom yang menentangnya. Ini karena tindakan politik apa pun mampu membentuk banyak hubungan rizomatik, termasuk hubungan dengan kekuatan yang dianggap berlawanan: “Garis-garis ini mengikat satu sama lain. Itulah mengapa seseorang tidak pernah bisa menempatkan dualisme atau dikotomi, bahkan dalam bentuk dasar dari yang baik dan yang buruk” (Deleuze, Guattari: 1988). Dengan cara ini, politik pluralisme empiris melampaui struktur oposisi yang sampai sekarang membatasi politik radikal. Ia melampaui ‘politik identitas’ di mana tuntutan politik didasarkan pada partikularitas tertentu atau identitas yang bertentangan dengan partikularitas lain—misalnya, yang didasarkan pada pertanyaan tentang gender, seksualitas, etnis dan sebagainya. Politik identitas didasarkan pada logika oposisi biner, yang merupakan salah satu ciri pemikiran aborescent yang akan ditolak oleh Stirner dan Deleuze. Logika identitas dibentuk melalui pertentangan dengan identitas lain. Namun politik rizomatik, seperti yang telah kita lihat, menolak oposisi biner tersebut, sebaliknya, ia menekankan keragaman koneksi antar identitas. Bidang politik juga merupakan sistem rizomatik: banyak koneksi terbentuk antara identitas yang berbeda—bahkan jika mereka bertentangan—sehingga membuka kemungkinan yang baru dan tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, menempatkan identitas tertentu dari oposisi—untuk berpikir hanya dalam kerangka penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki, gay oleh straight, kaum kulit hitam oleh kaum kulit putih dan lain sebagainya—adalah untuk membatasi kemungkinan politik kita. Oleh karena itu, politik pluralisme empiris dapat dilihat sebagai upaya untuk melampaui kategori politik yang ada dan untuk menciptakan yang baru—untuk memperluas bidang politik di luar batasnya saat ini, dengan membuka kedok koneksi yang dapat dibentuk antara perlawanan dan kekuasaan yang dilawan. Seperti yang dikatakan Deleuze: “Anda dapat membuat patahan, menarik garis terbang, namun masih ada bahaya bahwa Anda akan memulihkan segalanya, bentukan yang memulihkan tenaga ke penanda” (Deleuze, Guattari: 1988).
Jadi, meskipun pernyataan tentang perbedaan identitas dengan hak-hak tertentu ini mungkin tampak sebagai ekspresi politik logis dari pluralisme empiris, Stirner dan Deleuze akan menolak politik semacam itu berdasarkan esensialisasi perbedaan. Sementara mereka menganggap perbedaan sebagai prinsip utama dunia korporeal, mereka juga melihat identitas esensial sebagai yang secara fundamental membatasi perbedaan. Kategori yang esensial meningkatkan perbedaan ke tingkat generalitas dan justru inilah yang mereka lawan. Perbedaan bagi Deleuze dan Stirner, non-konseptual, non-esensialis dan secara konstitutif terbuka untuk berubah dan menjadi. Ia adalah tentang multiplisitas dan kemungkinan, daripada mencapai identitas tetap. Begitu perbedaan mencapai identitas tetap—setelah itu dinaikkan ke tingkat ‘sakral’, dalam kata-kata Stirner—ia kemudian menjadi penindas dan seketat totalitas yang ditentangnya. Perbedaan harus dibiarkan terbuka—terbuka untuk ‘yang lain’, terbuka bahkan untuk kemungkinan ‘yang sama’.
Dengan cara ini, politik pluralisme empiris tetap terbuka untuk ‘yang lain’. Ia terbuka bagi dimensi universal yang melampaui partikularitas dan perbedaan mutlak. Dalam hasratnya untuk melawan kemungkinan totalisasi dari yang universal, politik partikular menegaskan logika totalisasi negara dan kapitalisme sebagai gantinya. Orang dapat berargumen bahwa justru karena politik dari partikular menghindari dimensi universal, maka ia akhirnya menegaskan kembali dominasi. Artinya, karena politik partikular menolak gagasan apa pun tentang yang universal, ia adalah ‘non-politik’—politik yang menyangkal makna atau signifikansi apa pun terhadap dimensi politik (Zizek: 2000)
Potensi radikalisme politik identitas—antagonisme nyata yang tampaknya diyakini—dihancurkan dalam penolakannya terhadap yang universal. Karena ia menolak yang universal, maka politik identitas tidak dapat menghadirkan tantangan bagi struktur umum kekuasaan dan dominasi. Di sisi lain, pluralisme empiris mengandaikan medan politik perbedaan yang tetap terbuka secara konstitutif terhadap kemungkinan-kemungkinan yang universal, dimensi politik vital yang disangkal oleh politik identitas.
Keterbukaan perbedaan terhadap yang universal ini mungkin paling baik diteorikan dengan gagasan singularitas, daripada partikularitas. Partikularitas adalah penutupan perbedaan dengan yang universal, sedangkan singularitas menunjukkan ketidaktegasan tertentu antara perbedaan dan universal. Kita telah melihat cara di mana yang umum atau universal dipertanyakan dari perspektif perbedaan, sebagaimana yang telah melampauinya. Sisi lain dari strategi pluralisme empiris ini adalah bahwa perbedaan kini dipertanyakan dari sudut pandang universal—ia terbuka untuk sesuatu yang melampaui batasnya sendiri. Misalnya, tulisan-tulisan Michel Foucault tentang revolusi membuktikan penghormatan yang mendalam atas ruang universal. Dia menganjurkan sikap anti-strategis pada pertanyaan perlawanan: “untuk menghormati ketika sesuatu yang tunggal muncul” (Foucault: 1981). Pendekatan anti-strategis ini, menurut saya, adalah pertahanan yang kuat dari dimensi universal dalam politik. Bagi Foucault, domain universalitas ini adalah sumber pemberontakan—ia adalah cakrawala kosong di mana setiap aksi atau perjuangan politik, tidak peduli seberapa spesifik, memberi penghormatan. Ia adalah domain yang penting bagi politik dan ia harus dipertahankan dari serbuan kekuasaan. Ketika kekuasaan “melawan yang universal”, ketika negara atau kekuasaan yang mendominasi mencoba untuk menutup domain ini, untuk mengisi tempat kosongnya, maka kita harus mempertaruhkan nyawa kita untuk mempertahankannya. Foucault juga berbicara tentang penghormatan terhadap ‘singularitas’. Namun yang dimaksud dengan singularitas, Foucault tidak berarti partikularitas dalam arti identitas politik tertentu. Sebaliknya, yang dia maksud adalah sejenis peristiwa tunggal yang kemunculannya tidak dapat diprediksi dan sampai batas tertentu tidak dapat dijelaskan.
Dari sini orang dapat mengembangkan sikap politik-etis singularitas—politik yang tidak menekankan perbedaan dengan mengesampingkan universalitas atau universalitas dengan mengesampingkan perbedaan, tetapi tetap menghidupkan ketidakmampuan mendasar di antara mereka. Lagipula, singularitas menyiratkan etika dan politik kehidupan—ia merujuk pada perjuangan hidup empiris dengan pluralitas dan persatuannya; kolektivitas dan individualitasnya; perbedaan dan universalitasnya, melawan abstraksi idealis yang menyangkalnya. Singularitas adalah ekspresi politik dan etika dari kekayaan dan intensitas korporeal. Ia dapat dilihat, seperti yang telah saya katakan, sebagai ekspresi politik-etis dari pluralisme empiris Stirner dan Deleuze.
*untuk versi pdf-nya sila unduh di sini