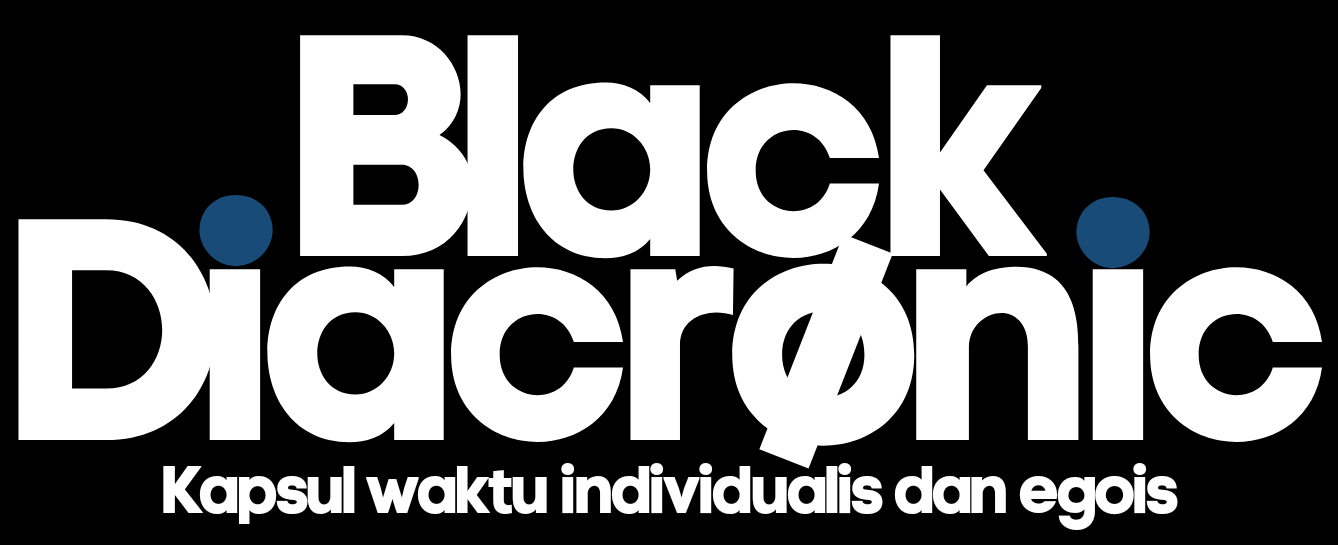Spectre of Marx (1993) karya Jacques Derrida mengeksplorasi logika spektralitas yang menghantui Marx. Marx terbukti terlibat dalam ‘perburuan hantu’ idealisme. Max Stirner adalah target penting bagi Marx, karena Stirner telah mengungkap sisa-sisa idealisme yang masih menghantui karya Marx. Paper ini akan mengeksplorasi pertanyaan spektralitas pada Stirner. Saya berpendapat bahwa logika spektralitas sangat penting dalam kritikannya terhadap ideologi, yang memungkinkan dia untuk melampaui pemahaman esensialis dan strukturalis tentang mekanisme ideologis. Yang esensial tentang ideologi, di mana ideologi dipandang sebagai distorsi irasional dari kepentingan esensial subjek dan strukturalis, di mana subjek dilihat benar-benar ditentukan oleh mekanisme ideologis; keduanya mengarah pada kematian dini ideologi sebagai sebuah konsep. Intervensi Stirner memungkinkan kita menghembuskan kehidupan baru ke dalam konsep ideologi dengan melampaui batas-batas problematikanya. Sebagai salah satu ahli teori ideologi pertama, Stirner dapat dibaca dalam sudut pandang ‘post-strukturalis’ kontemporer, dalam kritiknya terhadap humanisme dan identitas esensialis. Tidak seperti pemikir post-strukturalis lainnya, Stirner tidak mengabaikan masalah ideologi; sebaliknya ia menunjukkan cara di mana gagasan dominasi ideologis dapat dipertahankan sambil menolak gagasan bahwa terdapat esensi manusia yang kepentingan aslinya disalahartikan oleh mekanisme ideologis. Dia membalikkan paradigma rasionalis humanis dengan menunjukkan bahwa esensi manusia itu sendiri adalah ‘hantu’ ideologis, yang hubungannya dengan kekuasaan harus dibuka kedoknya. Namun, dia melampauinya dengan berteori tentang kelebihan spektral, yang lolos dari determinasi ideologis dan bertindak sebagai titik tolak non-esensialis di mana kritik terhadap ideologi dapat dibangun.
Stirner telah ditafsirkan dengan berbagai cara. Dia dilihat sebagai seorang nihilis, eksistensialis, anarkis dan libertarian. Marx melihatnya sebagai ‘ideolog borjuis kecil’ dan sebagai pemikir idealis yang terjebak dalam dunia ilusinya sendiri. Namun pentingnya Stirner sebagai ahli teori ideologi sebagian besar telah diabaikan oleh kritik kontemporer. Karyanya adalah demonologi mekanisme ideologis—‘gagasan tetap’ (fixed idea) dari humanisme Abad Pencerahan, seperti esensi manusia, kebenaran rasional dan moralitas. Dia terlibat dalam proyek ikonoklastik guna mengungkap gagasan-gagasan yang kita anggap remeh; mengungkap hubungan kekuasaan dan antagonisme di balik wajah humanis dan rasionalis mereka yang tenang. Bagi Stirner, ‘gagasan tetap’ adalah gagasan yang esensial dan dijadikan ‘sakral’. Ia telah menjadi sistem yang tertutup secara diskursif, dihapus dari genggaman individu dan menahannya, sebagai tindakan pencabutan kekuatan individu. Terdapat unsur penaklukan dan penindasan agama dalam mekanisme ideologis. Logika religius yang dibongkar Stirner ini akan dibahas nanti, namun penting untuk dicatat bahwa Stirner adalah salah satu orang pertama yang secara sistematis menganalisis sistem ideologis. Dalam melakukannya, dia melampaui cara para materialis tentang ideologi yang mereduksinya menjadi epiphenomenon hubungan sosial borjuis. Menurut Stirner, ‘gagasan tetap’ memiliki logika internalnya sendiri, di luar cara kerja ekonomi kapitalis.
Kritik Marx Terhadap Idealisme
Hal ini muncul sebagai perbedaan krusial antara Stirner dan Marx. Seperti yang akan kita lihat nanti, tuduhan utama Marx terhadap Stirner adalah bahwa Stirner telah mengabaikan realitas sebagai basis material ideologi. Dalam The German Ideology (1846), Marx dan Engels mengembangkan dua perbedaan teori ideologi dan dalam beberapa hal, mereka saling kontradiktif. Pertama, ini adalah kritik terhadap Idealisme Jerman, yang dianggap Marx dan Engels lazim bagi filsuf Hegelian Muda, seperti Feuerbach, Bauer dan Stirner. Menurut mereka, para filsuf ini adalah ideolog karena mereka mengabstraksi gagasan dan kesadaran dari basis mereka di realitas, dunia material, untuk mengubahnya menjadi hantu metafisik di dunia lain. Bagi Marx dan Engels, ‘para ideolog Jerman’ telah membalikkan keadaan yang sebenarnya, melihat bahwa dunia material ditentukan oleh gagasan, padahal pada kenyataannya, gagasan ditentukan oleh dunia material dan praktik sosial yang konkret. Mereka berkata:
Bertentangan langsung dengan filsafat Jerman yang turun dari surga ke bumi; permasalahannya naik dari bumi menuju surga. Artinya, bukan berangkat dari apa yang dikatakan, dibayangkan dan dikandung, atau dari manusia yang diceritakan, dipikirkan, dibayangkan dan dikandung agar sampai pada manusia; tetapi berangkat dari orang-orang yang benar-benar aktif dan berdasarkan proses kehidupan nyata mereka, menunjukkan perkembangan reflektif ideologis mereka dan gema dari proses kehidupan ini.
Dengan kata lain, gagasan dan kesadaran adalah cerminan dari kehidupan material, dari aktivitas dan proses konkret yang dilakukan manusia. Proses material inilah yang menentukan kesadaran dan bukan sebaliknya. Untuk membalikkan hubungan tersebut, menyembunyikan basis material dari gagasan-gagasan dan melihat gagasan-gagasan sebagai entitas yang abstrak dan otonom yang menentukan dunia material, seperti yang dituduhkan oleh Marx dan Engels kepada para filsuf idealis, adalah sebuah isyarat ideologis. Dengan kata lain, ideologi adalah distorsi dari hubungan nyata antara kehidupan dan gagasan, penyamaran dari dasar kesadaran material.
Pemahaman kedua tentang ideologi yang ditemukan dalam The German Ideology adalah masalah politik, di mana yang pertama dapat dikatakan bersifat epistemologis. Bagi Marx dan Engels, ideologi dapat dijelaskan sebagai cerminan dominasi kelas. Mereka berkata: “Gagasan kelas penguasa yang ada di setiap zaman adalah gagasan yang berkuasa…Gagasan-gagasan yang berkuasa tidak lebih dari ekspresi ideal dari hubungan material yang dominan” (Marx dan Engels: 1976). Dengan demikian, ideologi selalu merupakan ekspresi dari dominasi kelas ekonomi. Kelas penguasa juga merupakan produsen gagasan—gagasan yang melegitimasi dan melanggengkan kekuasaan mereka. Terlebih lagi, gagasan yang berkuasa menghasilkan ilusi universalitas, sehingga kepentingan kelas penguasa selalu ditampilkan sebagai kepentingan bersama. Menurut Marx dan Engels, setiap kelas penguasa baru “harus memberikan gagasan-gagasannya dalam bentuk universalitas dan menampilkannya sebagai satu-satunya yang rasional, valid secara universal” (Marx dan Engels: 1976). Ideologi dengan demikian melibatkan ilusi atau penipuan tertentu—ia menyajikan kepentingan tertentu dari sebuah kelas, sebagai kepentingan umum universal bagi semua orang. Ia adalah sejenis ‘kamera obskura’ yang melakukan inversi dari yang partikular dan universal, untuk menutupi kepentingan tertentu dengan memberikan semua orang tampilan universalitas dan rasionalitas, sehingga melegitimasi kelas mereka. Setiap kelas penguasa baru yang menggantikan yang lama, mempengaruhi pembalikan ideologis ini. Misalnya, kepentingan nyata kaum borjuis—untuk mengeksploitasi kaum proletar secara ekonomi—disamarkan sebagai kepentingan universal umat manusia. Dengan cara ini, kaum proletar tertipu melalui representasi ideologis yang keliru ini untuk mengidentifikasi kepentingannya dengan kepentingan kelas borjuis. Ideologi menghalangi kaum proletar untuk mengidentifikasi kebenarannya, kepentingan mereka yang sebenarnya—yang akan menggulingkan hubungan sosial borjuis—dan dengan demikian, melanggengkan hubungan eksploitatif dan penindasan. Dalam teori Marx, ideologi melibatkan distorsi, ia berfungsi mengaburkan hubungan kelas borjuis tentang dominasi dan eksploitasi dan membutakan kaum proletar dengan kepentingan esensial dirinya sendiri. Menurut Engels, kaum proletar mengalami ‘kesadaran palsu’, di mana mereka tertipu atas kepentingan yang sebenarnya oleh mekanisme ideologis yang melukiskan gambaran ilusi universalitas, rasionalitas dan relasi sosial kelas borjuis yang tak terelakkan.
Kedua pemahaman ideologi yang disajikan di sini sangat berbeda. Gagasan pertama tentang ideologi melihatnya sebagai abstraksi gagasan dari basis dasarnya realitas, kehidupan material—sebuah distorsi epistemologis. Yang kedua melihat ideologi dalam arti politik yang lebih langsung sebagai serangkaian gagasan yang dihasilkan oleh kelas penguasa, yang menutupi partikularitasnya dalam kedok universalitas, sehingga menimbulkan ‘kesadaran palsu’. Terdapat kontradiksi utama dalam hal ini. Apakah ideologi yang telah menyamarkan fakta bahwa gagasan tidak memiliki pengaruh yang menentukan terhadap kehidupan material dan sosial? Ataukah ideologi merupakan rangkaian gagasan yang berperan aktif dalam mendukung dan memelihara sistem hubungan sosial tertentu? Apakah ideologi adalah yang mengabstraksi gagasan dari realitas? Atau apakah ia adalah senjata dalam perjuangan politik dan relaitas sosial? Dengan kata lain, teori pertama melihat ideologi sebagai abstraksi gagasan dari kehidupan material dan sosial, sedangkan teori kedua menempatkan ideologi dalam gagasan-gagasan aktual itu sendiri dan peran yang mereka mainkan dalam perjuangan material yang sangat nyata. Yang terakhir memungkinkan ideologi memiliki peran yang lebih internal dalam kehidupan material daripada yang sebelumnya, yang melihatnya murni sebagai abstraksi dari kehidupan material (Eagleton: 1991).
Namun saya berpendapat, bahwa terlepas dari perbedaan-perbedaan ini, dua jenis ideologi yang dikemukakan oleh Marx dan Engels, memiliki satu pengertian yang krusial: keduanya melihat ideologi berkaitan dengan ilusi fundamental—distorsi dan mistifikasi realitas. Gagasan pertama tentang ideologi melihatnya sebagai penyamaran dari gagasan material dan sosial. Yang kedua, melihat ideologi sebagai penciptaan ilusi universalitas; menutupi partikularitas kepentingan kelas borjuis dan dengan demikian, menipu kaum proletar demi kepentingannya sendiri yang esensial. Ideologi, dalam kedua pengertian itu, menyiratkan ilusi, tipu muslihat atau penipuan—distorsi mendasar dari realitas. Gagasan ideologi ini mengikuti logika rasionalisme, di mana kebenaran rasional disandingkan dengan mengaburkan mekanisme ideologis yang mendistorsi kebenaran. Ideologi dalam arti pertama, mendistorsi hubungan nyata antara kehidupan material dan gagasan, dan dalam pengertian kedua, ia menyamarkan realitas kekuasaan kelas dan kepentingan rasional dan realitas dari kaum proletar. Kaum proletar tidak dapat memahami kebenaran dari kepentingan-kepentingannya yang sebenarnya, karena dalam hal ini, mereka tertipu oleh mekanisme ideologis. Ideologi sebagai penipuan menyiratkan kebenaran rasional atau gagasan tentang kepentingan nyata yang sedang terdistorsi. Oleh karena itu, ideologi pada dasarnya tidak rasional.
Paradigma Ideologi:
Rasionalisme dan Strukturalisme
Pendekatan ideologi ini berakar pada rasionalisme Abad Pencerahan. Abad Pencerahan mengklaim membawa ‘cahaya terang akal budi ke air takhayul yang gelap dan keruh’ mistifikasi agama. Pemikiran ilmiah dan rasional dipandang sebagai alat yang akan membebaskan manusia dari kebingungan dan tirani. Jika hubungan hak ilahi diekspos dan ternyata ia tidak rasional, maka ia akan digulingkan. Menarik, seperti yang dikatakan Terry Eagleton, bahwa para pemikir Abad Pencerahan yang berusaha mengembangkan sistem gagasan rasional dan membawa rasionalisme untuk mendukung obskurantisme, pertama kali dikenal sebagai ideolog atau ideologues (Eagleton: 1991). Namun bagi Marx, seperti yang telah kita lihat, istilah ‘ideologi’ selalu dikaitkan dengan mistifikasi dan distorsi kebenaran rasional. Jelaslah bahwa, terlepas dari pembalikan istilah, teori ideologi Marx dan Engels menganut logika rasionalis Abad Pencerahan, di mana pengetahuan rasional dan ilmiah dipandang sebagai penangkal gagasan yang mengaburkan dan ilusi. Dalam kasus Marx dan Engels, materialisme atau materialisme-historis, justru merupakan penangkal ilmiah dari mistifikasi ideologis. Lebih penting lagi, berhubungan dengan Marx dan Engels, terdapat gagasan tentang kepentingan esensial dan yang nyata dari kaum proletar, yang telah disalahartikan karena cara kerja ideologi borjuis, dan ia hanya dapat dipahami secara tepat dan rasional melalui studi ilmiah yang nyata, realitas historis. Dengan kata lain, terdapat kebenaran esensial dan rasional tentang masyarakat dan inti kepentingan esensial dalam subjektivitas kaum proletar sebagai sebuah kelas, yang tersembunyi di bawah lapisan mistifikasi ideologis dan kesadaran palsu dan sedang menunggu untuk ditemukan.
Esensialisme ini penting bagi logika rasionalisme Abad Pencerahan: terdapat subjek yang pada dasarnya rasional dan moral yang hanya perlu memahami rasionalitas dan moralitas yang melekat untuk membebaskan dirinya dari obskurantisme metafisik dan otoritarianisme politik, yang membuatnya terikat. Ia adalah bahasa filsafat politik humanis Abad Pencerahan; mulai dari liberalisme hingga anarkisme: manusia diperbudak oleh ketidaktahuannya sendiri, dan jika saja dia dapat mengembangkan kemampuan rasional dan moral bawaannya, dia dapat membebaskan dirinya dari penindasan politik. Dengan kata lain, terdapat identitas esensial yang realisasi rasionalnya terdistorsi atau disangkal oleh ideologi. Seseorang harus menghilangkan rintangan ideologis ini, untuk mengusir ‘hantu’ yang membingungkan ini dengan diskursus ilmiah dan rasional, agar esensi manusia dapat terwujud. Di sini kita dapat berkata bahwa, terdapat titik tolak, berupa subjektivitas manusia yang esensial dan diskursus ilmiah yang rasional, yang tidak tercemar oleh ideologi. Dalam istilah rasionalis Abad Pencerahan, selalu terdapat sudut pandang non-ideologis—subjek dan diskurusus yang pada dasarnya rasional yang dapat melangkah keluar dari mekanisme ideologis dan merefleksikannya secara kritis. Ilmu rasional adalah penangkal distorsi ideologis. Misalnya Bakunin yang menggembar-gemborkan sains rasional sebagai “sains yang telah melepaskan diri dari semua hantu metafisika dan agama” (Bakunin: 1964). Bagi Marx, diskursus rasional ekstra-ideologis juga merupakan materialisme-historis. Dengan kata lain, meskipun persepsi subjek tentang kepentingan yang sebenarnya terdistorsi oleh ideologi, kepentingan tersebut tetap berada di luar ideologi dan dapat dipahami secara rasional dan ilmiah. Jika ideologi melibatkan distorsi, pasti terdapat kebenaran atau esensi rasional yang terdistorsi dan ini memberikan titik tolak kritis di luar ideologi. Justru dari sudut pandang di luar mekanisme ideologis ini—titik berangkat yang tidak terkontaminasi ini—ideologi dapat dikritik sebagai distorsi yang tidak rasional. Oleh karena itu, pemahaman rasionalis Abad Pencerahan tentang ideologi berpendapat bahwa kita dapat melangkah keluar dari ideologi, yang dapat kita lihat melalui distorsi dari sudut pandang epistemologis tertentu. Bagi Marx dan Engels, pemahaman tentang logika sejarah akan memungkinkan kaum proletar untuk melepaskan ‘kesadaran palsu’ dan akhirnya memahami kepentingannya yang sebenarnya, sehingga mereka menjadi ‘sadar kelas’. Tentu saja keistimewaan epistemologis ini hanya dapat dicapai oleh tingkatan tertentu bagi kaum proletar, yang dalam kata-kata Marx, “memiliki keuntungan dari pemahaman yang jelas tentang garis gerakan” (Marx: 1848).
Namun, dapatkah kita keluar dari ideologi dengan cara ini? Dapatkah kita terlibat dalam kritik rasional terhadap ideologi dari jarak yang aman, dari titik berangkat yang tidak terkontaminasi di luarnya? Sebuah pandangan ‘strukturalis’ tentang ideologi akan berpendapat bahwa posisi ekstra-ideologis yang tidak tercemar ini tidak pernah ada dan kita tidak dapat melangkah keluar dari mekanisme ideologis. Memang untuk menempatkan titik yang menguntungkan di luar ideologi, yang darinya kita dapat merefleksikan ideologi secara rasional, ia sendiri merupakan isyarat ideologis. Dengan kata lain, tidak ada kesenjangan antara ideologi dan subjek—tidak ada pembagian antara distorsi ideologis dan pemikiran rasional. Kesenjangan ini sendiri merupakan distorsi ideologis. Ideologi telah menjajah tempat ini dan berpikir bahwa kita dapat keluar dari ideologi hanya untuk menegaskan posisi kita di dalamnya. Izinkan saya menjelaskan pemikiran strukturalis ini dengan mengacu pada Althusser. Bagi Althusser, tidak ada esensi manusia di luar jangkauan ideologi, seperti yang diharapkan oleh para pemikir rasionalis Abad Pencerahan. Memang teori ideologi Althusser adalah pemutusan radikal dengan bentuk-bentuk humanis dari Marxisme. Sebaliknya subjek manusia dikonstruksi atau diinterpelasi oleh mekanisme ideologis. Althusser di sini membalikkan paradigma di mana subjek merupakan ideologi: “kategori subjek hanya merupakan konstitutif dari semua ideologi sejauh semua ideologi memiliki fungsi (yang mendefinisikannya) sebagai upaya ‘membentuk’ individu konkret sebagai subjek” (Althusser: 1971). Struktur ideologis, atau yang oleh Althusser disebut sebagai ‘Aparatus Ideologi Negara’, menghasilkan subjek melalui kesalahan pengenalan dan distorsi yang merupakan inti dari reproduksi sosial. Tidak ada ‘kesadaran palsu’ dalam pemikiran ini. Subjek tidak tertipu dengan kepentingannya yang sebenarnya dan esensial, karena kepentingan tersebut tidak pernah ada atau lebih tepatnya, mereka dibangun oleh Aparatus Ideologi Negara. Tidak ada titik tolak rasional yang esensial di luar ideologi—ideologi ada di sekitar kita, yang ada sebagai dasar keberadaan sosial. Bagi Althusser, ideologi itu abadi—tidak ada yang dapat melampaui interpelasi ideologis.
Kita memiliki dua pemikiran tentang ideologi yang sangat berlawanan: pemikiran rasionalis Abad Pencerahan, di mana ideologi dipandang sebagai distorsi irasional dari kepentingan rasional dan esensial subjek; dan pemikiran strukturalisme, di mana gagasan tentang kepentingan esensial diabaikan dan subjek dibentuk oleh struktur ideologis. Saya telah menyatakan bahwa pemahaman pertama tentang ideologi memberikan titik tolak yang tidak terkontaminasi di luar ideologi, di mana seseorang dapat secara rasional merefleksikannya, sedangkan posisi kedua tidak memungkinkan titik pandang yang diistimewakan seperti itu. Tidak ada celah di sini antara ideologi dan subjek. Masalah ideologi miring pada dua kutub yang berlawanan ini.
Akhir dari Ideologi?
Selain itu, dapat dikatakan bahwa posisi yang sangat berbeda ini telah menyebabkan stagnasi teoretis ideologi sebagai sebuah konsep. Pemikiran rasionalis Abad Pencerahan, guna melihat ideologi sebagai distorsi realitas yang tidak rasional, harus mengandaikan subjektivitas esensial di luar ideologi. Ia mengandalkan titik berangkat yang tidak terkontaminasi di mana ideologi dapat dilawan. Namun, seperti yang dikemukakan oleh para strukturalis, konsep sudut pandang istimewa di luar ideologi ini tidak dapat dipertahankan lagi. Ia bergantung pada gagasan esensialis dan metafisik yang meragukan tentang subjektivitas. Sebaliknya, ideologi telah menjajah subjek dan menempatkan kesenjangan antara ideologi dan subjek sebagai isyarat ideologis terakhir. Namun, kritik strukturalis terhadap posisi humanis Abad Pencerahan, memberi kita sejumlah masalah dan melemparkan konsep ideologi ke dalam krisis. Pertama, tanpa titik tolak di luar ideologi, bagaimana ideologi dapat dianalisis dan dilawan? Jika subjek sudah ditentukan oleh ideologi, bagaimana mungkin terdapat konsepsi kritik politik terhadap struktur ideologis yang, misalnya, mempertahankan kekuasaan rezim yang represif, atau mendukung praktik eksploitatif dan merusak lingkungan? Kedua, jika tidak terdapat tempat di luar ideologi atau jika ideologi telah menjajah celah non-ideologis, di mana ideologi dipandang sebagai distorsi atau ilusi, lalu bagaimana kita dapat terus mendefinisikan konsep ideologi? Bagaimana kita membedakannya dari praktik lain? Konsep ideologi, dalam kata-kata Zizek, telah tumbuh “terlalu kuat”, dan akibatnya menjadi tidak berarti: “ia mulai merangkul segalanya (Zizek: 1994). Gap yang memisahkan ideologi dari pemahaman rasionalnya, berfungsi sebagai gap konstitutif yang memungkinkan ideologi didefinisikan berlawanan dengan sesuatu. Setelah celah atau titik berangkat tersebut dihilangkan, maka ideologi menjadi tidak mungkin untuk didefinisikan. Dengan kata lain, jika ideologi adalah segalanya, maka ia bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, pertanyaan tentang ideologi terjebak dalam kebingungan: jika ia mempertahankan gagasan ideologi sebagai distorsi kebenaran rasional, maka ia dapat mempertahankan titik berangkat yang tidak terkontaminasi di luar ideologi, namun ia harus bergantung pada klaim esensialis palsu; atau, jika ia meninggalkan kategori esensialis, ia kehilangan sudut pandang ekstra-ideologis dan jatuh ke dalam perangkap memperluas konsep ideologi ke titik di mana ia kehilangan nilai teoretis. Seperti pendapat Zizek, konsep ideologi yang berlebihan ini adalah “salah satu alasan utama secara progresif ditinggalkannya gagasan ideologi” (Zizek: 1994).
Apa bentuk pengabaian ideologi tersebut? Dua tanggapan utama terhadap krisis ideologi adalah perluasan logis dari dua pemikiran ideologi yang sangat bertentangan yang telah diuraikan di atas. Tampaknya pemikiran rasionalis Abad Pencerahan tentang ideologi menemukan kesimpulan logisnya dalam pengabaian rasionalis Habermas terhadap tesis ideologi. Habermas menyajikan teori komunikasi rasional dan non-koersif di mana ideologi tidak memiliki tempat. Bagi Habermas, selalu ada kemungkinan komunikasi yang tidak terdistorsi antar subjek dan ini mengandaikan pemahaman intersubjektif universal: “Namun para partisipan dalam aksi komunikatif harus mencapai pemahaman tentang sesuatu di dunia , ika mereka berharap untuk melaksanakan rencana aksi mereka atas dasar kesepakatan” (Habermas: 1990). Dengan demikian, subjek dapat mencapai pemahaman rasional tentang dunia melalui tindak tutur yang mengacu pada konteks tersebut, tanpa efek distorsi ideologi. Gagasan Habermas tentang tindakan komunikatif menganut pemahaman rasionalis Abad Pencerahan tentang dunia. Ideologi masih dipandang sebagai distorsi pemahaman dan komunikasi. Namun di dunia komunikasi yang sempurna tersebut, konsep ideologi sama sekali tidak memiliki tempat—efek distorsinya dapat dengan mudah dilewati oleh konsensus rasional yang dicapai melalui ‘situasi berbicara yang ideal’. Jadi, dalam istilah Habermasian, ideologi telah menjadi usang—ia tidak lagi memiliki relevansi teoretis atau politik.
Namun, bukankah Habermas, dalam upaya untuk melewati distorsi ideologis melalui ‘situasi pidato yang ideal’, terbuka untuk tuduhan yang sama bahwa ketika seseorang mencoba melampaui ideologi, ia hanya menegaskan kembali posisinya di dalam ideologi itu sendiri? Seperti yang telah saya kemukakan sebelumnya, tempat non-ideologis tersebut, apakah ia mengambil bentuk esensi manusia atau konsensus rasional yang dicapai secara intersubjektif, ia sendiri adalah ideologis. Mencoba keluar dari ideologi adalah isyarat ideologis yang paling utama. Mungkin sirkularitas argumen ini, tesis ‘ideologi ada di mana-mana’ yang mengarah pada pelemahan ideologi sebagai sebuah konsep, yang telah mendorong jenis kedua dari ditinggalkannya ideologi, ‘poststrukturalisme’. Pengabaian ideologi poststrukturalis dapat dilihat sebagai kesimpulan logis dari posisi strukturalis. Strukturalisme menolak gagasan tentang subjektivitas manusia yang esensial, melainkan subjek diproduksi oleh perangkat ideologis dan akibatnya, tidak terdapat tempat berangkat yang tidak terkontaminasi di luar ideologi. Ia membawa kepada masalah utama bahwa jika konsep ideologi diperluas untuk mencakup segala sesuatu, maka ia kehilangan makna. Mengapa tidak menyingkirkan ideologi saja? Apakah ia terus memiliki nilai secara konseptual atau politik? Bukankah lebih relevan dan efektif untuk melihat dunia dalam hal diskursus, praktik dan strategi kekuasaan? Inilah yang dilakukan Foucault. Bagi Foucault, tidak penting untuk berpikir dalam kerangka distorsi ideologis, karena ia menyiratkan bahwa terdapat beberapa kebenaran rasional, representasi menjadi terdistorsi dan justru gagasan tentang kebenaran absolut inilah yang dipertanyakan oleh Foucault. Bagi Foucault, yang diragukan bukanlah representasi kebenaran, tetapi status ontologis dan epistemologis dari kebenaran itu sendiri: “pertanyaan politik…bukanlah kesalahan, ilusi, kesadaran yang teralienasi atau ideologi; ia adalah kebenaran itu sendiri” (Foucault: 1980). Dengan kata lain, jika status kebenaran itu sendiri diragukan, maka pertanyaan tentang distorsi ideologis tentang kebenaran tidak relevan lagi. Yang lebih penting adalah hubungan dan praktik kekuasaan yang tercakup dalam diskurusus mengenai kebenaran. Selain itu, bagi Foucault, tidak ada subjektivitas manusia yang disangkal atau ditipu oleh ideologi—subjek adalah produk, fabrikasi. Namun, subjek tidak dibentuk oleh ideologi, seperti yang dikatakan Althusser, melainkan dihasilkan oleh kekuasaan dan diskursus. Ia jelas non-ideologis karena tidak ada distorsi, bahkan distorsi konstitutif, seperti yang terjadi pada Althusser. Foucault melihat praktik dan strategi material yang digunakan untuk membangun subjektivitas—misalnya, cara tahanan diproduksi sebagai subjektivitas yang teralienasi melalui teknik pengawasan dan penahanan yang beroperasi di penjara (Foucault: 1991). Tidak terdapat penipuan ideologis di sini, melainkan serangkaian praktik, teknik dan strategi kekuasaan yang menghasilkan subjek. Melalui konsep ‘kekuasaan’-nya, Foucault telah menempatkan ideologi sebagai fokus analitis—kekuasaan tersebar di seluruh jaringan sosial, di semua tingkatan dan terlibat dalam tindakan serta hubungan kita sehari-hari; praktik kita yang paling kecil sekalipun: “kekuasaan ada di mana-mana karena ia datang dari segala penjuru” (Foucault: 1978).
Namun terdapat masalah di sini. Jika kekuasaan, bagi Foucault, tersebar di mana-mana, maka seperti halnya ideologi, ia tidak dapat dijelaskan dan kehilangan nilai konseptualnya. Kekuasaan telah menjadi konsep yang terlalu luas, dengan cara yang sama, ketika ideologi sebagai konsep diperluas ke pada titik ketidakberartian. Harus ada juga kesenjangan konstitutif antara kekuasaan dan subjek, sama seperti perlu adanya kesenjangan antara ideologi dan subjek. Inilah poin yang dibuat oleh Ernesto Laclau dan Lilian Zac. Mereka berpendapat bahwa kekuasaan tidak dapat berada ‘di mana-mana’, seperti yang dikatakan Foucault, karena jika ada, ia kehilangan identitasnya sebagai ‘kekuasaan’ (Laclau dan Zac: 1996). Agar kekuasaan ada sebagai sebuah konsep, perlu adanya ‘kekurangan’ konstitutif yang membatasinya secara definisi. Kekurangan ini dihapuskan dalam formulasi kekuasaan Foucault dan oleh karena itu, identitas kekuasaan itu sendiri menjadi tidak berarti. Foucault, dalam arti tertentu, telah menggantikan ideologi dengan kekuasaan dan juga telah memperluas konsepnya secara berlebihan. Jadi kita mungkin berkata, seperti yang kita lakukan dengan ideologi, bahwa jika kekuasaan adalah segalanya, maka ia bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, jika kekuasaan tersebar luas dalam arti, seperti yang dikatakan Foucault, maka sulit untuk berteori perlawanan terhadap kekuasaan. Ini adalah masalah yang dihadapi Foucault dan tidak pernah bisa diselesaikan.
Terdapat masalah lain yang lebih menarik dengan pengabaian ideologi yang bersifat ‘poststrukturalis’ dan diskursif. Ini mewakili upaya lebih lanjut untuk melangkah keluar dari ideologi. Kali ini, bukan dari perspektif subjek yang otonom dan esensial, tetapi secara paradoks; melalui penolakan terhadap identitas esensial. Dengan kata lain, ia adalah upaya untuk melampaui problematis ideologi dengan menepisnya di tempat diskursus dan praktik yang menjadi subjek. Sementara penempatan jaringan kekuasaan dan diskursus yang tersebar di mana-mana, seharusnya menyangkal kemungkinan sudut pandang kritis di luar jaringan, dan dengan cara yang ironis, juga menyangkal pemikir ‘poststrukturalis’ itu sendiri dari sudut pandang obyektif; ini adalah sebuah isyarat ideologis. Seperti pendapat Zizek, inilah ‘jebakan terakhir’ ideologi: kita telah melihat bahwa upaya kaum rasionalis untuk memisahkan ideologi dari realitas dan menempatkan titik tolak yang tidak terkontaminasi di luar ideologi adalah ideologis itu sendiri. Namun untuk menanggapi hal ini dengan sepenuhnya menolak gagasan tentang realitas ekstra-ideologis dan untuk melihat dunia hanya dalam hal fabrikasi diskursif, dengan kata lain, untuk menyerah sepenuhnya pada kemungkinan sudut pandang kritis guna merefleksikan ideologi, maka ia sendiri ideologis. Bagi Zizek, “solusi ‘postmodern’ yang cepat dan licin adalah ideologi par excellence.” (Zizek: 1994). Dengan kata lain, posisi ‘postrukturalis’ agak tidak jujur, yang dengan rendah hati menyangkal dirinya dari sudut pandang netral dengan melihat suaranya sendiri sebagai satu diskursus di antara banyak diskursus; secara paradoks, ia mengasumsikan pandangan ‘obyektif’ di atas pluralitas yang tak ada habisnya, diskursus dan kekuasaan, dan ini tentu saja ideologis. ‘Poststrukturalisme’, dengan berpegang pada keyakian, bahwa kita harus meninggalkan seluruh problematis ideologi karena ia mengandaikan esensi non-ideologis yang tidak pernah ada, namun secara bersamaan, ia melakukan dua tindakan yang kontradiktif. Ia mencoba untuk keluar dari ideologi, sementara pada saat yang sama, menyangkal kita, tempat di luar ideologi. Apa yang dimaksud dengan ini adalah, penegasan kembali ideologi, atau lebih tepatnya, upaya seseorang untuk menghindarinya. Dalam kata-kata Zizek, “keluar dari ideologi adalah bentuk perbudakan kita terhadapnya.” (Zizek: 1994). Ideologi terus bermunculan di berbagai tempat, di mana kita berpikir bahwa kita telah menghindarinya. Mungkin ini juga menegaskan kembali ideologi atau ‘perbudakan’ konseptual; mungkin harus kita katakan, ia juga berhutang pada ideologi.
Jadi sepertinya kita kembali ke awal. Saya telah menunjukkan bahwa rasionalisme Abad Pencerahan yang ditentang secara radikal dan pandangan strukturalis tentang ideologi telah menyebabkan stagnasi dan secara progresif ditinggalkannya ideologi sebagai sebuah proyek. Saya juga telah menunjukkan bahwa pengabaian ideologi ini telah mengambil dua bentuk yang sangat bertentangan: pendekatan Habermasian, yang sejalan dengan posisi rasionalis Abad Pencerahan dan pendekatan ‘poststrukturalis’ Foucauldian yang merupakan perpanjangan dari pandangan strukturalis tentang ideologi. Selain itu, saya telah menunjukkan cara di mana dua penolakan ideologi sebagai sebuah konsep akhirnya gagal dan dalam upaya mereka untuk membuang ideologi, keduanya mengarah pada penegasannya kembali ideologi. Jadi, tampaknya tidak ada jalan untuk keluar dari ideologi. Namun pembahasan sejauh ini telah menghasilkan beberapa kesimpulan yang menarik. Pertama, ideologi tidak dapat lagi diteorikan sebagai distorsi hakikat manusia. Diskusi-diskusi strukturalis dan bahkan post-strukturalis, telah menunjukkan bahwa subjek adalah produk ideologi, dan upaya untuk menempatkan titik tolak yang tidak terkontaminasi di luar ideologi, ia sendiri adalah ideologis. Kedua, dan secara paradoks juga sangat jelas, kita tidak dapat menyajikan kritik terhadap ideologi atau bahkan memiliki gagasan yang berarti jika ideologi sama sekali, tanpa titik tolak ini, tanpa sudut pandang kritis dan radikal di luar struktur ideologi. Kita harus memiliki ‘ruang’ ekstra-ideologis untuk merefleksikan mekanisme ideologi, karena jika tidak, kritik terhadap ideologi tidak dapat berlanjut lebih jauh dan ‘akhir dari ideologi’, seperti yang telah dikatakan, akan baik-baik saja dan benar-benar bersama kita. Tampaknya ini adalah dua persyaratan yang kontradiktif: bahwa teori ideologi harus menolak identitas esensialis, sehingga menyangkal sudut pandang ekstra-ideologis dari pemikiran rasionalis Abad Pencerahan, dan pada saat yang sama, harus mempertahankan titik berangkat ekstra-ideologis untuk menjadi teori kritis ideologi.
Intervensi Stirner:
Menuju Kritik Hantu Ideologi
Menurut saya, teorisasi ideologi Stirner memberikan jalan keluar yang mungkin dari kebingungan ini. Kritiknya terhadap ideologi melampaui rasionalis Abad Pencerahan dan penjelasan strukturalis tentang ideologi serta memenuhi dua kondisi teoretis yang tampaknya kontradiktif yang telah saya uraikan—bahwa teori ideologi mempertahankan titik tolak di luar ideologi, namun menolak gagasan tentang otonom, subyek esensial. Dia melakukannya melalui reformulasi radikal subjek ideologis. Sisa dari diskusi akan dikhususkan untuk mengeksplorasi teori ideologi Stirner dan mengembangkan logika spektralitasnya, yang akan memberikan petunjuk penting bagi teorisasi ulang ideologi kontemporer.
Tampaknya, dari problematis yang diuraikan di atas, ideologi adalah momok yang mustahil. Ia adalah penampakan yang datang untuk menghantui kita, meskipun kita berusaha keras untuk mengusirnya dan menghilang ketika kita mencoba mendekatinya. Namun, mungkin dengan mengakui bahwa tidak dapat diaksesnya hal ini, spektralitas ideologi, kita dapat mulai memahaminya. Stirner yakin bahwa ideologi adalah hantu-hantu atau momok yang menghantui manusia modern:
Lihatlah secara dekat atau jauh, dunia hantu mengelilingi Anda di mana-mana; Anda selalu mengalami ‘penampakan’ (Erscheinungen)’atau penglihatan. Segala sesuatu yang tampak bagi Anda hanyalah khayalan dari roh yang berdiam, adalah ‘penampakan’ hantu; dunia bagi Anda hanyalah sebuah ‘dunia penampakan’ (Erscheinungswelt), di belakangnya roh berjalan (Stirner: 2012).
‘Penampakan’ tersebut adalah ‘gagasan tetap’—abstraksi ideologis seperti esensi, kebenaran rasional, moralitas, yang telah diubah menjadi ‘yang sakral’. ‘Gagasan tetap’ adalah konstruksi yang mengatur pikiran—suatu kemutlakan yang tertutup secara diskursif yang memutilasi perbedaan dan pluralitas keberadaan. Sistem ideologis mengandung gagasan-gagasan opresif yang menghantui individu dengan menghadapkannya dengan standar yang mustahil dicapai individu. Seperti yang Stirner nyatakan: “Astaga, kepala Anda dihantui…Anda membayangkan hal-hal hebat dan menggambarkan kepada diri Anda sendiri seluruh dunia dewa yang memiliki keberadaan untuk Anda, alam roh yang menurut Anda akan memanggil Anda, sebuah ideal yang mengundang Anda.” (Stirner: 2012). Ideologi adalah rangkaian gagasan, tujuan dan janji ilusi yang menginterpelasi individu, menciptakan ideal dan impian yang mustahil ia kejar. Di sini terbukti bahwa ideologi dipandang sebagai ilusi atau distorsi yang mengasingkan individu.
Jika hanya ini yang ada pada teori ideologi Stirner, maka itu hanya akan menjadi perpanjangan dari pemahaman rasionalis Abad Pencerahan, di mana ideologi dilihat sebagai sistem gagasa yang menyimpang yang mengasingkan individu dari kepentingan esensial—dari esensi manusianya. Namun jika kita melihat lebih dekat, Stirner mewakili pemisahan paradigmatik dengan humanisAbad Pencerahan dan membangun teori ideologi non-esensialis yang sangat berbeda.
Kritik Humanisme
‘Perpecahan epistemologis’ dengan humanisme esensialis ini dapat dilihat dalam kritik radikal Feuerbach. Dalam Essence of Christianity (1841), Ludwig Feuerbach menerapkan pengertian alienasi pada agama (Feuerbach: 1957). Menurut Feuerbach, agama itu mengasingkan, karena ia mengharuskan manusia melepaskan kualitas dan kekuatannya sendiri dengan memproyeksikannya kepada Tuhan yang abstrak di luar jangkauan manusia. Dengan melakukan nya, manusia menggantikan dirinya yang hakiki, membuatnya terasing dan direndahkan. Kualitas-kualitas baik manusia menjadi abstrak darinya dan dia ditinggalkan dalam lokus kosong dosa, bersujud di hadapan Tuhan yang Mahakuasa dan Maha Pengasih: “Jadi dalam agama, manusia menyangkal akalnya…pengetahuannya sendiri, pemikirannya sendiri, sehingga dia dapat menempatkan mereka di dalam Tuhan. Manusia menyerahkan kepribadiannya…dia menyangkal martabat manusia, ego manusia” (Feuerbach: 1957). Bagi Feuerbach, predikat Tuhan sebenarnya hanyalah predikat manusia sebagai makhluk spesies. Tuhan adalah ilusi, hipostatisasi manusia. Sementara manusia harus menjadi satu-satunya kriteria bagi kebenaran, cinta dan kebajikan, karakteristik tersebut sekarang menjadi milik makhluk abstrak yang menjadi satu-satunya kriteria bagi mereka. Dengan kata lain, Tuhan adalah reifikasi esensi manusia, dari kualitas esensial manusia.
Akan tetapi, menurut Stirner, dalam mengklaim bahwa kualitas-kualitas yang kita kaitkan dengan Tuhan atau Yang Mutlak sebenarnya adalah kualitas-kualitas esensial manusia, Feuerbach telah membuat manusia menjadi makhluk yang maha kuasa. Feuerbach melihat kehendak, cinta dan pikiran sebagai kualitas esensial dalam diri manusia, ingin mengembalikan kepadanya kualitas abstrak ini. Manusia, di mata Feuerbach, menjadi ekspresi tertinggi dari cinta, pengetahuan, kehendak dan kebaikan. Ia menjadi mahakuasa, suci, sempurna, tak terbatas—singkatnya, manusia menjadi Tuhan. Feuerbach mewujudkan proyek humanis Abad Pencerahan untuk mengembalikan manusia ke tempat yang selayaknya di pusat alam semesta, menjadikan manusia sebagai yang ilahi, yang terbatas menjadi yang tak terbatas. Manusia sekarang telah merebut Tuhan. Dia telah menangkap untuk dirinya sendiri kategori yang tidak terbatas.
Stirner memulainya dengan menerima kritik Feuerbach terhadap agama Kristen: ketidakterbatasan adalah ilusi, yang hanya merupakan representasi dari kesadaran manusia. Agama Kristen didasarkan pada diri yang terbagi dan teralienasi; orang beragama mencari alter egonya yang tidak dapat dicapai karena telah diabstraksikan ke dalam sosok Tuhan. Dengan melakukan itu, dia menyangkal dirinya yang konkret dan sensual. Namun Stirner menanggapi ini:
Makhluk tertinggi memang esensi manusia, tetapi, hanya karena itu adalah esensinya dan bukan dia sendiri, tetap tidak penting apakah kita melihatnya di luar dirinya dan melihatnya sebagai ‘Tuhan’, atau menemukannya di dalam dirinya dan menyebutnya ‘esensi manusia’ atau ‘manusia’. Saya bukan Tuhan atau manusia, bukan esensi tertinggi atau esensi saya. Oleh karena itu, semuanya adalah satu yang utama apakah saya memikirkan esensi seperti di dalam diri saya atau di luar saya (Stirner: 2012).
Stirner bermaksud, bahwa dengan mencari yang sakral dalam ‘esensi manusia’, dengan menempatkan manusia yang esensial dan menghubungkannya dengan kualitas-kualitas tertentu yang sampai sekarang dikaitkan dengan Tuhan, Feuerbach hanya memperkenalkan kembali keterasingan agama. Dengan menjadikan karakteristik dan kualitas tertentu penting bagi manusia, Feuerbach telah mengasingkan mereka yang tidak memiliki kualitas tersebut. Dan dengan demikian manusia menjadi seperti Tuhan dan seperti manusia direndahkan di bawah Tuhan, demikian pula individu direndahkan di bawah makhluk yang sempurna ini, manusia. ‘Pemberontakan’ Feuerbach tidak menggulingkan kategori otoritas keagamaan—ia hanya menempatkan manusia di dalamnya, membalik urutan subjek dan predikat. Bagi Stirner, manusia sama menindas, jika tidak lebih, daripada Tuhan: “Feuerbach berpikir, jika dia memanusiakan yang ilahi, dia telah menemukan kebenaran. Tidak, jika Tuhan telah memberi kita rasa sakit, ‘manusia’ mampu mencubit kita lebih menyiksa lagi” (Stirner: 2012). Manusia menjadi pengganti ilusi Kristen. Menurut Stirner, Feuerbach adalah pendeta dari sebuah agama baru, humanisme: “Agama manusia hanyalah metamorfosis terakhir dari agama Kristen” (Stirner: 2012). Manusia humanis adalah mekanisme ideologis baru, distorsi ilusi baru yang menindas. Ia adalah gagasan yang memutilasi dan mengasingkan, seperti yang disebut Stirner, ia adalah ‘hantu’,atau ‘gagasan tetap’. Ia adalah hantu ideologis yang menodai keunikan dan perbedaan individu dengan membandingkan individu dengan ideal yang bukan ciptaannya sendiri. Dengan cara ini, individu menjadi terintepelasi oleh hantu—subjektivitasnya dibangun di sekitar esensi yang penuh ilusi. Momok Tuhan/Manusia ini, hantu humanisme, menghantui Stirner di sepanjang karyanya.
Kita dapat melihat di sini betapa radikalnya Stirner menginversikan pemahaman humanis Abad Pencerahan tentang ideologi sebenarnya. Sementara Stirner mempertahankan gagasan ideologi sebagai distorsi, ia meninggalkan gagasan tentang esensi manusia yang terdistorsi. Justru esensi manusia itu sendiri adalah distorsi ideologis, mekanisme penindasan dan alienasi. Jadi, dalam rumusan Stirner, tidak ada subjek manusia yang otonom dan esensial yang tertipu oleh ideologi. Sebaliknya, subjektivitas esensial ini sendiri telah dikonstruksi oleh mekanisme ideologis. Gagasan esensi, rahasia besar diskursus humanis yang suatu hari nanti akan terwujud, bagi Stirner, adalah hantu ideologis, ilusi. Kita juga dapat melihat cara logika spektralitas Stirner melampaui teori ideologi klasik. Pada pengertian pertama, spektralitas diterapkan pada ideologi dalam pengertian klasik; kita dihantui oleh ilusi, ‘gagasan tetap’ atau ‘hantu’ yang menipu kita. Namun, dalam pengertian kedua, manusia sendiri telah menjadi hantu, ilusi ideologis yang diciptakan oleh ‘pembalikan’ agama humanis. Manusia, dalam arti tertentu, dihantui dan diasingkan oleh dirinya sendiri, oleh momok ‘esensi’ di dalam dirinya: “Sejak saat itu, manusia tidak lagi, dalam kasus-kasus tertentu, gemetar pada hantu di luar dirinya, tetapi pada dirinya sendiri; dia takut pada dirinya sendiri” (Stirner: 2012). Dalam teori Stirner, tidak ada titik tolak esensialis di luar sistem ideologis, esensi itu sendiri adalah ideologis.
Bagi Stirner, hantu ideologis esensi manusia ini pada dasarnya menindas dan terkait dengan dominasi politik. Sama seperti Tuhan adalah kekuatan yang menaklukkan individu, sekarang hal itu adalah manusia, dan seperti yang dikatakan Stirner, “’Manusia’ adalah Tuhan hari ini, dan ketakutan akan manusia telah menggantikan ketakutan lama akan Tuhan” (Stirner: 2012). Esensi manusia telah menjadi norma baru yang dengannya individu diadili dan dihukum: “Saya menetapkan apa itu ‘manusia’ dan apa yang bertindak dengan cara yang ‘benar-benar manusiawi’, dan saya menuntut setiap orang agar hukum ini menjadi norma dan ideal baginya; jika tidak, dia akan mengekspos dirinya sebagai ‘seorang pendosa dan kriminal” (Stirner: 2012). Dengan kata lain, karena identitas tertentu telah dikonstruksikan sebagai ‘esensial’, ia menciptakan standar ideologis yang sesuai dengan apa yang diharapkan individu. Jadi esensi manusia adalah mesin baru hukuman dan dominasi: norma baru yang mengutuk perbedaan.
Foucault juga telah melihat bagaimana gagasan tentang apa yang merupakan ‘manusia’ telah menjadi norma baru penghukuman dan keterasingan, terutama di penjara dan dalam diskursus psikiatri. Perlakuan humanisme terhadap kejahatan sebagai penyakit yang harus disembuhkan adalah contoh cara diskursus hukuman itersebut berfungsi. Seperti pendapat Stirner:
Sarana kuratif atau penyembuhan hanyalah kebalikan dari hukuman; teori penyembuhan berjalan paralel dengan teori hukuman; jika yang terakhir melihat perbuatannya sebagai dosa terhadap hak-hak, maka yang pertama menganggapnya sebagai dosa manusia terhadap dirinya sendiri, sebagai seorang yang ‘murtad’ dari kesehatannya (Stirner: 2012).
Inilah tepatnya argumen Foucault tentang formula hukuman modern dalam Discipline and Punish: The Birth of the Prison (1975): sebuah formula di mana norma medis dan psikiatri hanyalah bentuk moralitas lama dalam wujud yang baru. Bagi Stirner dan juga Foucault, hukuman hanya dimungkinkan dengan membuat sesuatu yang sakral, sesuatu yang bisa dilanggar. Ada homologi tertentu di sini antara Stirner dan Foucault yang belum dieksplorasi. Kedua pemikir tersebut menyajikan kritik terhadap humanisme, mengungkap praktik dominasi dan keterasingan yang terlibat dalam diskursus tersebut. Saya akan berargumen bahwa Stirner melampaui argumen ‘poststrukturalis’ dengan berteori titik berangkat di luar ideologi /kekuasaan, di mana perlawanan terhadap diskursus humanis ini dapat terjadi, sesuatu yang Foucault tidak dapat merumuskannya secara memadai.
Kritik politik-ideologis Stirner terhadap humanisme dan esensi manusia dikembangkan dalam kontra-dialektika. Sementara dialektika Hegel memuncak pada kebebasan umat manusia, kontra-dialektika yang memetakan perkembangan umat manusia dalam kaitannya dengan institusi politik yang sesuai dengannya, berakhir dengan dominasi ideologis individu. Analisisnya dimulai dengan liberalisme atau yang oleh Stirner disebut sebagai ‘liberalisme politik’ (political liberalism). Seperti yang ditunjukkan oleh Stirner, kebebasan politik hanya berarti bahwa negara bebas, sebagaimana kebebasan beragama berarti bahwa agama itu bebas: “ia tidak mengandaikan kebebasan saya, tetapi kebebasan suatu kekuasaan yang mengatur dan menundukkan saya” (Stirner: 2012). Dengan kata lain, kebebasan yang diemban oleh liberalisme hanya terbatas pada subjektivitas dan diskursus politik tertentu yang diatur oleh negara—ia selalu melibatkan dominasi lebih lanjut. Tahap kedua dari kontra-dialektika adalah ‘liberalisme sosial’ (social liberalism) atau sosialisme. Liberalisme sosial muncul sebagai penolakan terhadap liberalisme politik yang dianggap terlalu egois (Stirner: 2012). Bagi Stirner, liberalisme politik dicirikan bukan oleh terlalu banyak egoisme, tetapi oleh terlalu sedikitnya egoisme dan dia melihat kesetaraan sosialisme yang dipaksakan, persamaan kemiskinan, sebagai penindasan lebih lanjut terhadap individu. Alih-alih ‘properti’ individu yang dimiliki oleh negara, kini dimiliki oleh masyarakat (Stirner: 2012). Menurut Stirner, individu telah berada di bawah kekuasaan abstrak di luar dirinya. Ini adalah salah satu poin di mana Stirner dan Marx berkonflik (Marx: 1976). Stirner, berbeda dengan Marx, tidak percaya pada masyarakat: ia melihatnya sebagai abstraksi lain, ilusi ideologis lainnya, seperti Tuhan dan esensi manusia, bahwa individu dikorbankan untuk: “Masyarakat, di mana kita memiliki segalanya, adalah tuan baru, hantu baru” (Stirner: 2012). Individu, menurut Stirner, bukanlah bagian penting dari masyarakat seperti yang diyakini Marx.
Jadi bagi Stirner, sosialisme hanyalah perpanjangan dari liberalisme: keduanya adalah sistem yang mengandalkan esensi yang dianggap sakral, negara dan hukum bagi liberalisme politik; dan masyarakat bagi liberalisme sosial. Stirner kemudian memeriksa bentuk ketiga dan terakhir dari liberalisme dalam dialektika ini: ‘liberalisme manusia’ (humane liberalism), atau humanisme. Liberalisme manusia didasarkan pada kritik terhadap liberalisme politik dan sosial. Bagi para humanis, kedua liberalisme ini masih terlalu egois: seseorang harus bertindak tanpa pamrih, murni atas nama kemanusiaan antar sesama. Namun seperti yang telah kita lihat, humanisme didasarkan pada gagasan tentang esensi manusia, yang menurut Stirner, adalah ideologis dan ilusi. Humanisme berpendapat bahwa setiap orang memiliki, di dalam diri mereka, sebuah inti esensial kemanusiaan yang harus mereka jalani. Jika mereka melanggar esensi tersebuti, mereka akan dianggap ‘tidak manusiawi’. Stirner ingin menegaskan hak individu untuk tidak menjadi bagian dari kemanusiaan, untuk menolak esensi manusia dan menciptakan kembali diri sendiri seperti yang dipilih. Bagi Stirner, humanisme adalah tahap terakhir dalam pembebasan manusia dan perbudakan ego individu. Semakin manusia membebaskan dirinya dari kondisi obyektif yang mengikatnya, seperti negara dan masyarakat, maka ia semakin didominasi ego individu, ‘keinginan diri’. Ini karena manusia dan esensi manusia telah menaklukkan benteng terakhir individu, pemikiran atau ‘pendapatnya’. Pendapat pribadi menjadi ‘opini umum manusia’ dan dengan demikian, otonomi individu terhapuskan (Stirner: 2012). Fantasi humanis Abad Pencerahan tentang pembebasan manusia, sekarang terpenuhi, karena ia sejalan dengan pelengkap dominasi individu.
Ideologi dan Kekuasaan
Bagi Stirner, humanisme adalah pandangan dunia ideologis di mana kita telah terperangkap. Humanisme sebagai ideologi, mengklaim telah membebaskan individu dari segala macam penindasan institusional, sementara pada saat yang sama, ia memerlukan intensifikasi penindasan atas diri kita sendiri, melalui esensi manusia, dan menyangkal kekuataan untuk menolak penundukan diri ini. Di sini, individu hanya memiliki kedaulatan semu. Dalam bahasa humanis tentang hak dan kebebasan terdapat jebakan: hak dan kebebasan diberikan kepada individu sebagai imbalan atas pelepasan kekuasaannya atas dirinya sendiri. Ideologi humanis merupakan, dalam kata-kata Stirner, “feodalisme baru di bawah kekuasaan manusia” (Stirner: 2012). Tempat penting dari dominasi ideologis humanis ini adalah moralitas. Stirner percaya bahwa moralitas bukan hanya fiksi yang diturunkan dari idealisme Kristen, tetapi juga diskursus yang menindas individu. Moralitas hanyalah puing-puing sisa dari agama Kristen, dalam pakaian humanis baru, dan seperti yang dikatakan Stirner: “Iman moral sama fanatiknya dengan iman agama!”(Stirner: 2012). Yang menjadi keberatan Stirner bukanlah moralitas itu sendiri, tetapi fakta bahwa ia telah menjadi hukum yang sakral. Moralitas telah menjadi agama baru, agama sekuler, yang melaluinya individu menjadi subjek. Gagasan moral menguasai hati nurani, menyangkal kebebasan inderawi individu dan memaksakan rasa malu dan rasa bersalah. Stirner memperlihatkan kehendak untuk berkuasa, kekejaman dan dominasi di balik gagasan moral: “Pengaruh moral dimulai, di mana penghinaan itu bermula; ya, ia tidak lain adalah penghinaan itu sendiri, penghancuran dan pembengkokan amarah (mutes) hingga kerendahan hati (demut)” (Stirner: 2012). Moralitas memutilasi individu:
“Individu harus menyesuaikan diri dengan kode moral yang berlaku, jika tidak ia menjadi terasing dari ‘esensi’ nya. Selain itu, moralitas terkait langsung dengan dominasi negara: “kemarahan populer terhadap moral ini melindungi institusi polisi lebih dari yang dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara apa pun untuk melindunginya” (Stirner: 2012).
Di sini, Stirner mengungkap operasi ideologis baru yang menghindari teori abad ke-19; hubungan antara esensi manusia sebagai hantu ideologis dan kekuatan politik. Alih-alih negara secara langsung menindas manusia, seperti yang terjadi dalam paradigma politik klasik, Stirner menunjukkan bahwa kekuasaan negara berfungsi melalui manusia, membangunnya sebagai tempat penindasannya sendiri. Dengan kata lain, ideologi menginterpretasikan individu sebagai subjek negara. Manusia dibangun sebagai situs kekuasaan, sebuah unit politik yang melaluinya negara mendominasi individu: “Inti negara hanyalah ‘manusia’, ketidaknyataan, dan ia sendiri hanyalah ‘masyarakat manusia’ (society of men)” (Stirner: 2012). Negara menuntut agar individu menjadi manusia dan menyesuaikan diri dengan norma-norma ideologis tertentu, sehingga dia menjadi bagian dari masyarakat negara dan didominasi dengan cara tersebut: “Jadi negara mengkhianati permusuhannya dengan saya, dengan menuntut agar saya menjadi seorang manusia…memaksakan menjadi manusia atas saya sebagai sebuah kewajiban” (Stirner: 2012). Stirner dengan cara tersebut, menggambarkan proses subjekifikasi di mana kekuasaan berfungsi, bukan dengan menekan manusia, tetapi dengan mengkonstruksinya sebagai subjek politik.
Mungkin poin terpenting tentang analisis Stirner tentang ideologi adalah proses subjekifikasi. Sebagai subyek, kita dikonstruksi sedemikian rupa sehingga kita secara sukarela menyerahkan kewenangan kita kepada negara. Seperti dugaan Stirner, negara tidak dapat berfungsi hanya melalui represi top-down, karena hal ini akan mengekspos kekuasaanya dengan segala ketelanjangan dan kebrutalannya. Sebaliknya, negara bergantung pada kita yang membiarkannya mendominasi kita. Stirner tidak begitu tertarik pada kekuasaan itu sendiri, tapi pada alasan mengapa kita membiarkan diri kita didominasi. Stirner ingin menunjukkan bahwa perangkat ideologis tidak hanya peduli dengan masalah ekonomi atau politik; mereka juga berakar pada kebutuhan psikologis. Dominasi negara, menurut Stirner, bergantung pada kesediaan kita untuk membiarkannya mendominasi kita, pada keinginan kita yang terlibat untuk merepresi diri kita sendiri:
Negara tidak dapat dipikirkan tanpa dominasi (Herrschaft) dan perbudakan (Knechtschaft) atau ketertundukan (subjection)…Ia yang, untuk mempertahankan miliknya, harus mengandalkan ketiadaan kehendak orang lain adalah hal yang dibuat oleh orang lain; ‘tuan’ adalah sesuatu yang dibuat oleh pelayan. Jika ketertundukan berhenti, semuanya akan berakhir dengan dominasi (Stirner: 2012).
Stirner berpendapat bahwa negara itu sendiri adalah abstraksi ideologis, seperti Tuhan; dan ia hanya ada, karena kita mengizinkannya ada, karena kita melepaskan otoritas kita sendiri kepadanya dengan cara yang sama, ketika kita menciptakan Tuhan dengan melepaskan otoritas kita dan menempatkannya di luar diri kita sendiri. Apa yang lebih penting daripada institusi negara adalah ‘prinsip yang berkuasa’, gagasan tentang negara yang mendominasi kita (Stirner: 2012). Negara dan dominasi sebagian besar ada dalam pikiran rakyatnya. Kekuasaan negara benar-benar didasarkan pada kekuatan kita. Hanya karena individu tidak mengakui kekuasaan tersebut, karena ia merendahkan dirinya di hadapan otoritas, maka negara akan terus ada (Stirner: 2012). Marx berpendapat bahwa ini adalah contoh utama idealisme Stirner. Bagi Marx, Stirner adalah seorang pemikir yang hidup di dunia ilusinya sendiri, salah mengartikannya sebagai kenyataan. Kita harus ingat bahwa The German Ideology karya Marx dan Engels adalah kritik terhadap apa yang mereka lihat sebagai kecenderungan idealis untuk melihat gagsan dan kesadaran memiliki efek yang menentukan di dunia nyata, sehingga mengabaikan dasar material gagasan yang nyata. Stirner dikutuk di sini sebagai ‘Saint Sancho’, sosok kesatria dalam novel Don Quixote (1605), yang bertarung dalam pertempuran imajiner dengan musuh imajiner pula. Bagi Marx, analisis Stirner tentang negara sebagai hantu ideologis; ilusi yang lebih bertumpu pada kepercayaan rakyatnya daripada pada kekuatannya sendiri, mengabaikan hubungan ekonomi dan kelas yang membentuk basis material negara. Menurut Marx, ‘idealisme’ Stirner secara absurd memungkinkan negara untuk ‘dikehendaki’ dari keberadaannya, daripada dirusak melalui aktivitas politik dan sosial yang konkret: “Ini adalah ilusi lama bahwa mengubah hubungan yang ada hanya bergantung pada niat baik rakyat dan hubungan yang ada adalah gagasan”(Marx dan Engels: 1976).
Namun, ini adalah kesalahan yang serius dan disengaja dalam membaca Stirner. Alih-alih mengabaikan realitas kekuasaan politik, Stirner justru melihatnya sebagai kekuatan utama dalam masyarakat, bahkan lebih daripada kekuasaan ekonomi. Sebaliknya, dapat dikatakan bahwa Marx, yang pemikirannya terjebak dalam batasan-batasan sempit materialisme, yang mengabaikan pentingnya kekuasaan politik dengan mereduksinya menjadi hubungan ekonomi dan kelas. Dalam pengertian ini Marx-lah yang membuat negara menjadi hantu; refleksi ilusi dari hubungan kelas borjuis. Stirner hanya berpendapat bahwa negara didasarkan pada premis ilusi, ideologis, seperti halnya moralitas yang ingin dia singkapkan. Bagi Stirner, negara hanya ada sejauh kita membiarkannya ada. Bukankah tidak bisa dipungkiri bahwa aturan apa pun bergantung pada kesediaan kita untuk membiarkannya mengatur kita? Kekuasaan politik tidak bisa hanya bergantung pada paksaan; ia membutuhkan bantuan kita, kemauan kita untuk patuh. Jika hanya satu yang menyadari, kata Stirner, bahwa kekuasaan negara bergantung pada kekuatan kita, maka kekuasaan akan hancur. Inilah yang dia maksud ketika dia mengatakan bahwa kekuasaan negara tidak ada artinya: di satu sisi ia sangat nyata, tetapi di sisi lain, ia hanya demikian karena kita membiarkannya. Jadi, Marx menyerang teori negara Stirner pada dua bidang yang kontradiktif. Di satu sisi, dia berpendapat bahwa Stirner menganggap negara terlalu penting dengan melihatnya memiliki efek yang menentukan pada kelas borjuisi dan hubungan kelas (Marx dan Engels: 1976). Di sisi lain, Marx mengklaim bahwa Stirner mengabaikan realitas politik negara dengan melihatnya sebagai ilusi ideologis. Dengan kata lain, di satu sisi, menurut Marx, Stirner terlalu banyak mengaitkan kepentingan dan realitas dengan negara, dan di sisi lain, dia tidak cukup membiarkannya.
Stirner percaya bahwa negara harus diatasi sebagai gagasan sebelum dapat diatasi dalam realitas. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa negara baru tidak akan muncul menggantikan yang lama. Yang harus diserang adalah hasrat akan otoritas. Negara tidak menekan hasrat, melainkan menyalurkannya ke dirinya sendiri: “Negara mengerahkan dirinya untuk menjinakkan manusia yang memiliki hasrat; dengan kata lain, ia berusaha untuk mengarahkan keinginannya sendirian dan untuk memuaskan keinginan itu dengan apa yang ditawarkannya” (Stirner: 2012). Hasrat akan otoritas, cinta negara, inilah yang melanggengkan kekuasaan. Orang-orang didominasi, kata Stirner, karena mereka memang menginginkannya. Stirner adalah salah satu pemikir pertama yang mengeksplorasi hubungan antara hasarat dan kekuasaan. Dia mengungkap masalah yang tidak terlalu diperhitungkan oleh para ahli teori radikal pada zamannya, bahwa subjek dapat dengan mudah menginginkan dominasi mereka sendiri, sama seperti mereka menginginkan kebebasan. Inilah tema yang kemudian dikejar oleh para pemikir poststrukturalis, khususnya Deleuze dan Guattari (Deleuze dan Guattari: 1977).
Un-Man
Namun bagi Stirner, jika individu menjadi subjek dengan cara tersebut, sebagai tempat dominasinya sendiri, bagaimana kita bisa berteori tentang perlawanan terhadap sistem dominasi politik-ideologis yang dibongkar Stirner? Jika tidak ada esensi manusia yang otonom, jika subjeknya sendiri dikonstruksi oleh sistem ideologis yang sangat humanis yang mendominasi dirinya, atas dasar apa kita secara kritis dapat terlibat dengan mekanisme ini? Dalam teori ideologi Stirner, adakah sudut pandang ekstra-ideologis yang kritis, yang darinya kita dapat merumuskan strategi perlawanan? Ini adalah masalah, seperti yang telah saya katakan, dan memang poststrukturalisme, masalah tentang titik tolak yang tidak terkontaminasi. Karena Stirner telah menolak gagasan otonom, subjek penting, melihatnya sebagai artefak ideologis, apakah dia juga menyangkal dirinya memiliki titik tolak kritis? Saya berpendapat, bahwa Stirner berteori pada titik kritis ini berangkat di luar ideologi, yang tidak bergantung pada kategori esensialis. Dengan melakukan itu, dia melampaui dengan baik pemikiran humanis Abad Pencerahan dan strukturalis ideologi, dan memenuhi dua persyaratan yang bertentangan atas kritik ideologi yang telah diuraikan sebelumnya. ‘Tempat’ perlawanan ekstra-ideologis ini dimungkinkan melalui perumusan radikalnya tentang subjek ideologis.
Keuntungan utama dari gagasan Stirner tentang subjektivitas adalah bahwa subjek, meskipun dibentuk oleh ideologi, tidak pernah sepenuhnya ditentukan olehnya, seperti dalam pemikiran strukturalis. Bagi Stirner, selalu ada kemungkinan subjek menolak subjekifikasinya, melawan cara dia dikonstruksi. Identitas subjek ideologis tidak pernah lengkap, selalu ada ‘kekurangan’ dalam simbolisasi yang merongrong kepenuhan identitas. Dengan kata lain, interpelasi ideologis tidak pernah sepenuhnya menjelaskan individu: “tidak ada konsep yang dapat mengungkapkan saya, tidak ada yang ditetapkan. Esensi saya membuat saya lelah” (Stirner: 2012). Selalu ada sisa, sisa spektral, yang dihasilkan oleh simbolisasi ideologis, namun lolos dan memberikan titik perlawanan terhadapnya. Terdapat kekurangan dalam pencerminan ideologis, itik di mana subjek ideologis tidak sepenuhnya mencerminkan simbol dan citra ideologis, melainkan melampauinya. Dengan kata lain, ini dapat dilihat sebagai distorsi ideologi, distorsi dari distorsi. Ekses ini adalah apa yang Stirner sebut sebagai ‘the un-man’ (Unmensch) ; yang lain dari manusia, yang lain dari humanisme. Ia adalah hantu yang ‘kembali’, dalam pengertian Lacanian, untuk mengganggu penerapan identitas dan esensi yang tetap. “Tapi un-man (Unmensch) yang ada di suatu tempat dalam setiap individu, bagaimana dia dihentikan?…Di sisi manusia selalu berdiri un-man…Negara, masyarakat, umat manusia tidak dapat menguasai iblis ini” (Stirner: 2012). Ia adalah sisi lain dari manusia, sebuah kekuatan yang tidak dapat dibendung, baik ciptaan manusia maupun ancaman terhadapnya. Ia adalah ekses yang dihasilkan oleh interpelasi ideologis, yang menolak untuk menyesuaikan diri dengan esensi manusia, dengan idealnya manusia. Kata ‘un-man’ adalah “manusia yang tidak sesuai dengan konsep manusia, karena yang tidak manusiawi adalah sesuatu yang manusiawi yang tidak sesuai dengan konsep manusia” (Stirner: 2012). Mungkin ia dapat dianggap dalam pengertian Lacanian sebagai ‘real’ dari simbolisasi: kelebihan makna yang dihasilkan oleh ketidakmampuannya untuk ditorehkan di dalam makna, oleh ketidakmampuannya untuk ditandai. Bagi Lacan, sebagaimana kita ketahui, individu dihadapkan pada sederet penanda yang seharusnya mewakili dirinya. Namun, selalu ada makna berlebih yang luput dari pemaknaan ini (Lacan: 1977).
Sebagai ekses yang luput dari simbolisasi, ‘un-man’ dapat dilihat sebagai titik di luar ideologi dan figur perlawanan terhadapnya. Ia adalah sesuatu yang mengacaukan identitas subjek manusia yang esensial dengan melanggar batas-batas sempitnya dan mengungkap sifat sewenang-wenang dan kontingen dari hantu ideologis. Terlebih lagi, penting untuk melihat bahwa ‘un-man’ bukanlah suatu esensi. Ia tidak pernah ada sebelumnya pada individu, sebelum interpelasi ideologis. Sebaliknya, ‘un-man’ adalah kelebihan spektral yang dihasilkan melalui proses interpelasi; ia hanya muncul setelah identitas ‘esensial’ dibangun bagi individu. Dalam pengertian ini, ‘un-man’, daripada menjadi esensi, adalah kegagalan esensi itu sendiri, batas-batas simbolisasi ideologis. Ini adalah titik di mana ideologi rusak dan sifat kontingen operasinya terungkap. Dengan cara ini, ‘un-man’, sebagai batas simbolisasi ideologis, dapat memberikan titik tolak ekstra-ideologis non-esensialis, di mana kritik terhadap ideologi dapat dibangun. Ini memenuhi dua kondisi yang telah disebutkan di atas bagi kritik kontemporer terhadap ideologi: bahwa ia membuang subjek manusia esensialis; dan bahwa hal itu memungkinkan titik tolak kritis. Dengan cara ini, gagasan Stirner tentang ‘un-man’ sebagai ‘tempat’ non-esensialis untuk melawan ideologi, sejalan dengan pemahaman rasionalis dan strukturalis tentang ideologi dan memberikan dasar bagi kritik kontemporer.
Strategi Perlawanan
Bagaimana tindakan perlawanan terhadap ideologi ini dikonseptualisasikan? Stirner melihat subjek perlawanan ini muncul melalui apa yang dia sebut ‘pemberontakan’ (insurrection). Pemberontakan, tidak seperti revolusi di masa lalu, yang hanya berakhir dengan penegasan kembali kekuasaan yang ingin mereka gulingkan dan tidak bertujuan untuk menggulingkan institusi politik. Justru karena ideologi dan kekuasaan beroperasi pada tingkat subjek (hasrat, pemikiran dan gagasan) daripada institusi dan subjek sering kali merupakan tempat dominasi ideologis, Stirner berpendapat bahwa setiap perlawanan terhadap dominasi juga harus dimulai di tingkat subjek. Oleh karena itu, pemberontakan bukanlah pemberontakan subjek terhadap institusi politik, tetapi pemberontakan subjek terhadap dirinya sendiri, melawan identitas subjektivitasnya, yang dibangun secara ideologis. Ini dimulai, seperti yang dikatakan Stirner, “dari ketidakpuasan manusia terhadap diri mereka sendiri” (Stirner: 2012). Ia adalah penolakan terhadap esensi, pelarian dari subjektivitas esensial, yang mengarah pada dislokasi mekanisme politik-ideologis:
Revolusi bertujuan untuk peraturan baru; sedangkan pemberontakan membuat kita tidak lagi membiarkan diri kita diatur, tetapi untuk mengatur diri kita sendiri dan tidak menaruh harapan pada ‘institusi’. Ia bukanlah pertarungan melawan yang mapan, karena jika berhasil, yang mapan akan runtuh dengan sendirinya; ia hanya bertujuan keluar dari yang mapan (Stirner: 2012).
Berbeda dengan revolusi Marxis, misalnya, di mana subjek melepaskan belenggu ideologi dan dibiarkan berkembang sesuai dengan esensinya, pemberontakan Stirner adalah pemberontakan yang justru melawan esensi tersebut Ia meninggalkan gagasan tentang subjektivitas esensial yang hanya dapat diungkapkan setelah ideologi dihapuskan dan lebih tepatnya, mendesak subjek untuk merekonstruksi identitasnya sesuai pilihannya, di luar batasan esensi. Pemberontakan, dengan kata lain, bukanlah tentang menjadi apa yang ‘ada’, tetapi tentang menjadi apa yang ‘bukan’. Gagasan untuk menolak identitas esensial seseorang dan mengeksplorasi subjektivitas baru ini tentu saja merupakan ciri dari strategi poststrukturalis. Penekanannya adalah pada proses menjadi dan berubah, bukan pada pencapaian identitas yang stabil yang akan dijajah oleh kekuasaan.
Gagasan Stirner tentang perlawanan terhadap dominasi ideologis melibatkan strategi perubahan dan kemenjadian: ‘mengkonsumsi’ atau menghancurkan identitas seseorang dan menemukan kembali diri sendiri lagi. Ego, bagi Stirner, adalah unit dasar dislokasi; ia bukan esensi atau serangkaian karakteristik yang ditentukan, melainkan ketiadaan, creative nothingness dan terserah individu untuk menciptakan sesuatu darinya dan tidak dibatasi oleh esensi. Bagi Stirner, diri hanya ada untuk dikonsumsi:
Saya memulai dari pengandaian dalam mengandaikan diri sendiri; tetapi prasangka saya tidak berjuang untuk kesempurnaannya seperti ‘manusia berjuang demi kesempurnaannya’, tetapi hanya melayani saya guna menikmatinya dan mengkonsumsinya…Saya tidak mengandaikan diri saya sendiri, karena saya setiap saat menciptakan diri saya sendiri (Stirner: 2012).
Oleh karena itu, subjek perlawanan, ego, adalah sebuah proses; aliran terus menerus dari aliran yang menciptakan diri sendiri, yang terus menghindari esensi (Ferguson: 1982). Seperti yang ditunjukkan Stirner, karena ideologi berfungsi melalui penetapan identitas tetap dan esensial, ego adalah hantu/momok kontra-ideologis yang lolos dari subjekifikasi melalui penolakannya terhadap simbolisasi, keterbukaan konstitutifnya.
Pelarian dari ideologi ini, tentu saja, hanya sementara dan terbatas, tidak ada tempat terakhir selain ideologi yang dapat dilewati subjek. Tidak ada keadaan kebebasan tertinggi dari ideologi. Menurut Stirner, kebebasan hanyalah sebuah konsep negatif yang masih terikat dengan diskursus humanis esensialis; ia selalu mengedepankan ‘bebas dari’ sesuatu dan untuk memperjuangkannya adalah menunjukkan betapa kita masih diperbudak dengan konsep yang kita upayakan. membebaskan diri dari. Oleh karena itu, bagi Stirner, kebebasan adalah hantu ideologis: “Saya tidak dapat menciptakannya: Saya hanya dapat mengharapkannya dan bercita-cita kepadanya, karena ia tetap ideal; hantu” (Stirner: 2012). Menurut rumusan tersebut, maka untuk mencari kebebasan abadi dari ideologi, yang secara paradoks, adalah perbudakan terakhir kita padanya – itu adalah aspirasi ideologis. Kita akan jatuh ke dalam perangkap Habermasian yang membayangkan dunia komunikasi yang sempurna, bebas dari distorsi ideologis, yang tentu saja merupakan isyarat ideologis tertinggi. Sebaliknya, untuk melawan dominasi ideologis secara efektif, kita harus mengakui bahwa, sampai batas tertentu, ideologi akan selalu bersama kita. Kita harus, seperti yang disarankan Stirner, terus bekerja pada diri kita sendiri untuk melawan subjekifikasi ideologis dan menemukan kembali posisi kita dalam ideologi, mencari ‘garis pelarian’ darinya. Stirner menyebut strategi perlawanan permanen dan negosiasi ulang ini sebagai ‘properti’ (property). Properti adalah bentuk kebebasan positif, di mana individu menegosiasikan kembali subjektivitasnya, menciptakan bentuk kebebasannya sendiri, daripada diserahkan kepadanya sebagai bagian dari program revolusioner. Bagi Stirner: “Orang yang dibebaskan tidaklah penting, dia hanyalah orang yang telah dibebaskan seorang libertinus; seekor anjing yang menyeret rantai bersamanya: dia adalah orang yang tidak bebas dalam pakaian kebebasan, seperti keledai berkulit singa” (Stirner: 2012). Tidak ada gagasan universal tentang kebebasan; hanya ada gagasan kebebasan tertentu yang memaksa individu untuk menyesuaikan diri. Jadi kebebasan selain sebagai hantu ideologis, juga selalu membawa dominasi lebih lanjut. Properti adalah strategi yang dilakukan oleh individu untuk menegosiasikan kembali posisinya dalam jaringan ideologis untuk melawan dan membatasi dominasi. Dengan kata lain, hal itu memungkinkan kita untuk bekerja pada batas-batas ideologi, mencari celah dan titik dislokasi dalam bangunannya serta mempertanyakan cara kita diinterpelasi oleh ideologi.
Stirner memberikan jalan keluar dari kebingungan rasionalisme dan strukturalisme melalui rekonfigurasi spektral subjek ideologis. Sementara subjek dikonstruksi oleh ideologi, terdapat juga keterbukaan konstitutif dalam strukturnya. Subjek sebenarnya dibentuk oleh ekses hantu yang, meskipun dihasilkan oleh simbolisasi ideologis, melampauinya, dan dengan demikian, memperlihatkan batas-batas ideologi. Hal ini memungkinkan kita untuk berteori, seperti yang telah saya kemukakan, titik tolak ekstra-ideologis non-esensialis yang diperlukan untuk kritik kontemporer terhadap ideologi. Stirner mengeksplorasi, kemudian, dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, hubungan halus antara ideologi, subjektivitas, hasrat dan kekuasaan; melihat esensi bukan sebagai tempat yang tidak terdistorsi di luar ideologi, melainkan di jantung distorsi ideologis. Dia mencapai ‘pemutusan epistemologis’ dengan humanisme dan strukturalisme, menghadirkan kritik post-humanis, post-Marxis dan ‘post-strukturalis’, terhadap struktur ideologis. Stirner menempati titik penting intervensi dan perpecahan dalam kritik ideologi, menghembuskan kehidupan baru ke dalam konsep dan memajukan pemahaman kita tentang operasi politik-ideologis kontemporer.
*untuk versi pdf-nya sila unduh di sini